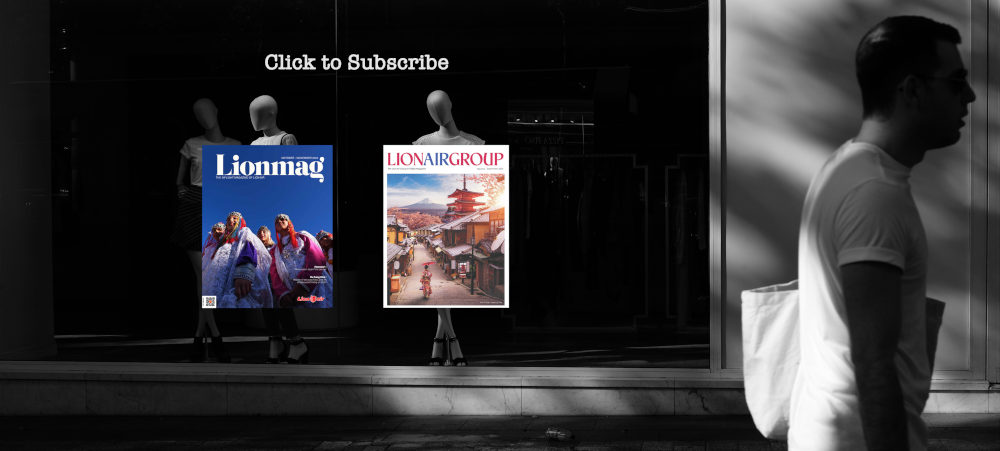Catatan dari Barcelona
Aku seorang peziarah yang ulet. Begitu aku memberi label pada diriku sendiri. Entah ini berlebihan atau malah merendah, bukanlah urusanku. Yang jelas, perjalanan mencermati setiap detail bangunan makin memperkuat pendapatku bahwa bangunan-bangunan yang dibuat manusia—para arsitek jaman dulu—sejatinya adalah rangkaian perjalanan sejarah hidup manusia. Aku beberapa kali mencermati dalam relief2 di Candi Borobudur.
Tak terkecuali pada tengah hari yang ramai di La Sagrada Familia, di Barcelona. Berdiri di dalam bangunan megah karya Antonia Gaudi ini serasa berdiri di alam semesta penuh pepohonan. Gaudi—lengkapnya, Antoni Gaudí (1852–1926) – Arsitek Catalonia, yang berjuluk “Arsitek Tuhan”, perancang utama Sagrada Familia; adalah seorang lelaki religius dan kontemplatif, yang memandang arsitektur sebagai karya Tuhan.
La Sagrada Familia adalah ‘alkitab dalam bentuk bangunan’. Demikian katanya. Meski meninggal dalam usia relative muda karena ditabrak kereta, tapi ia mewariskan disain mahakarya yang bahkan 100 tahun pun wujud disain itu belum jadi.
Ketika mengunjunginya pada 4 September 2025, kami masih mendapati perbaikan di sana sini. Dari puncak salah satu menara kami sempat melihat ada satu bulatan di tiang menara yang belum dipasang keramik warna warni.
Tidak puas dengan penjelasan guide kami—setiap peserta tour wajib membayar 40 Euro—aku mengambil posisi yang pas untuk mencermati fasad barat.
Di sisi barat La Sagrada Familia ini berdiri Fasad Penderitaan (Passion Facade), wajah gereja yang sepenuhnya berbeda dari fasad kelahiran. Bila fasad kelahiran penuh kehidupan, detail flora-fauna, dan simbol kebahagiaan inkarnasi, maka fasad penderitaan adalah kebalikannya: keras, sunyi, dingin, penuh sudut tajam, seakan dipahat langsung untuk menumbuhkan semcam rasa ngilu bagi yang melihatnya.
Begitu berdiri di pelataran belakang di sisi barat, persis di tengah area yang penuh manusia—'passion fasade’ itu segera menampakkan diri. Pandanganku tertarik ke dua pilar miring seperti tulang yang menopang serambi.
Di atasnya, garis-garis putih menyerupai mahkota duri raksasa membentuk lesplang atap—menciptakan bayang-bayang tajam di dinding batu yang kasar, seolah-olah batu itu sendiri “dicambuk”.
Di relung tertinggi fasad, tampak patung Yesus disalib—tubuhnya kurus, dipahat dengan bidang-bidang geometris. Hampir tanpa penutup, figur ini menampilkan totalitas penyerahan diri (sampai2 gambaran vulgar alat kelamin tampak jelas—pahatan yang menimbulkan kontraversi di natara banyak pengikutnya): lengan menegang, dada tertarik, perut cekung, luka terpahat jelas. Di bibir relung, tampak tengkorak kecil (Golgota) dan figur-figur yang meratap di bawah salib.
Yesus di salib dengan tubuh hampir telanjang—tanpa kain penutup sebagaimana lazimnya tradisi Katolik—adalah pusat dari fasad penderitaan ini. Sebuah gambaran yang kontroversial, bahkan terasa brutal. Tetapi di balik itu tersimpan simbolisme mistik yang dalam.
Dalam tradisi mistik Kristen, telanjang bukanlah vulgaritas, melainkan lambang kenosis—pengosongan diri. Yesus digambarkan tanpa penutup untuk menyampaikan bahwa pada saat pengorbanan puncak, Ia telah menanggalkan semua atribut duniawi: kuasa, martabat, bahkan penutup tubuh. Yang tersisa hanyalah jiwa yang berserah total kepada Bapa.
Tepat satu tingkat di bawahnya, sebuah panel bersudut-sudut menampilkan jalan ke Kalvari: di kanan tampak sosok menekuk memanggul salib, sementara di kiri berdiri figur-figur prajurit. Pada pusat panel menonjol perisai/medalion dengan wajah Kudus (kiasan kain Veronica).
Di ambang pintu tengah, sebuah tiang cambuk berdiri sendiri, dengan unsur simpul/tali—menandai flagelasi (Yesus dicambuk). Kengerian berkelebat dalam pikiranku membayangkan ini sebagaimana saat Sekolah Dasar dulu diceritakan seorang guru. Waktu SD saya memang sekolah di SD GMIM Teling Bawah.
Saat berdiri di hadapan fasad, mata saya tertarik ke sisi kiri. Di bagian atas, dalam sebuah relung, tampak sekelompok figur mengelilingi tubuh yang direbahkan. Adegan itu jelas menggambarkan penurunan Yesus dari salib—tubuh yang sudah tak bernyawa, dikelilingi wajah-wajah duka yang membisu. Ada keheningan pahit di sana, bahkan ketika dipahat dalam batu.
Lebih ke bawah, di atas balok, terpahat ayam jantan. Simbol sederhana ini justru menghentak batin saya: mengingatkan pada Petrus yang menyangkal Tuhannya tiga kali sebelum ayam berkokok. Sungguh sebuah tanda kecil, namun penuh bobot spiritual: betapa manusia bisa rapuh dan goyah di saat genting.
Tak jauh dari situ, di dinding tegak, terlihat sebuah persegi ajaib (Magic Square)—papan kotak angka 4×4. Baris, kolom, dan diagonalnya semua berjumlah 33—usia Kristus ketika wafat. Angka-angka itu tidak hanya permainan matematis, tapi simbol bahwa seluruh penderitaan ini bukan kebetulan, melainkan perjalanan hidup yang mencapai titik puncak pada angka suci itu. Di bawahnya terukir jelas “Mc 14,45”.
Ini simbol apa? Temanku om Google segera kutanyai: Mc 14,45" tampaknya merujuk pada Matius 14:45 dalam Alkitab, yang menggambarkan pembunuhan dan penjualan Yesus Kristus oleh Yudas Iskariot kepada para imam Yahudi. Beberapa buku yang pernah kubaca tentang ‘ciuman Yudas’—tanda pengkhianatan yang begitu tragis.
Di sampingnya, tampak figur berjubah yang menunduk, wajahnya tertutup bayang. Sebuah pahatan yang dingin, tapi menyayat: wajah pengkhianat yang tak bisa disembunyikan.
Di sisi kanan fasad tampak figur berlutut memegang sehelai kain. Ia adalah Santa Veronica, perempuan berani yang, di tengah kekejaman, justru maju untuk mengusap wajah Yesus. Pada kain itu, menurut tradisi, tercetak wajah Kudus. Adegan itu seakan menyelipkan secercah kasih di tengah derita.
Relung-relung lain di sisi ini penuh dengan figur-figur prajurit, saksi, dan orang-orang yang tampak membeku dalam duka. Semua dipahat dalam gaya patah, kaku, dan dingin khas Josep Maria Subirachs, seolah hendak menegaskan bahwa penderitaan ini tak bisa dilunakkan.
Subirachs (1927–2014) adalah pematung modernis yang merealisasikan sebagian besar Fasad Penderitaan berdasarkan warisan disain Gaudi. Ia menerjemahkan karya Gaudi itu dengan gaya ekspresionis-geometris yang tajam dan “dingin”. Aku melihat dengan detail apa yang dipahatkannya untuk menambah pengetahuanku tentang apa sebenarnya ‘penderitaan’ dalam kosnep Kristus, Gaudi dan Subirachs ini.
Lebih dari 30 menit berdiri di beberapa titik menghadap fasad itu, ku merasa fasad ini tidak sedang menceritakan sebuah kisah lama. Lebih tepat, ia sedang menghadirkan perjalanan batin: dari pengkhianatan, penyangkalan, sampai secercah keberanian dan kasih yang sederhana. Dan saya sendiri, sebagai peziarah, seperti sedang diajak untuk ikut memikul semua itu dalam diam.
Pada penglihatanku, seluruh permukaan teksturnya pasti kasar—seperti batu digaruk, ditusuk, dan dipahat cepat—yang berpeluang meninggalkan rasa sakit pada materialnya. Cahaya sore yang miring mempertegas kontras terang–gelap, sehingga penderitaan seakan bukan hanya diceritakan, tapi dihadirkan. Aku melihat sebuah perjalanan spiritual luar biasa dalam pengorbanan ini.
Kesanku, Gaudí merancang fasad ini untuk mengejutkan dan mengguncang jiwa, agar siapa pun yang melihatnya dapat merasakan kembali jalan salib Kristus. Tentu, sebagai muslim, aku melihat ini dalam konteks perjalanan spiritual seorang manusia. Tidak lebih, tidak kurang.
Jalan Derita sebagai Jalan Penyucian
Dalam kerangka mistik, penderitaan bukan sekadar fase gelap atau ujian, tetapi pintu gerbang transendensi. Gaudí melalui fasad penderitaan seakan hendak menyampaikan bahwa jalan derita adalah jalan penelanjangan jiwa—segala atribut duniawi dilucuti, hingga yang tersisa hanyalah inti terdalam dari diri manusia.
Ketelanjangan Kristus yang dipahat Subirachs tidak berhenti pada kontroversi estetika, melainkan menyiratkan kenosis: pengosongan total dari ego, kuasa, dan martabat. Pada kondisi inilah, jiwa manusia dimurnikan. Mistikus dari berbagai tradisi—entah Kristiani, Islam, Hindu, atau Buddha—sering menekankan bahwa puncak penyatuan dengan Yang Ilahi tidak mungkin dicapai tanpa jalan derita.
BACA JUGA : Nestapa yang Menari-nari: Flamenco dari Sacromonte
Penderitaan, dalam perspektif ini, adalah semacam ‘api penyucian’ yang membakar kesombongan, ambisi, dan ilusi diri. Seorang peziarah sejati tidak hanya mencari keindahan, tetapi berani menatap luka, pengkhianatan, penyangkalan, bahkan kehinaan—karena di situlah via purgativa (jalan penyucian) dimulai. Jalan salib bukan sekadar kisah Yesus, melainkan cermin perjalanan setiap manusia yang ingin sampai ke puncak: mati dari dirinya, agar hidup di dalam yang Kudus.
Berdiri di hadapan fasad ini, seorang peziarah muslim seperti saya, seperti ditantang: beranikah saya berjalan di jalur mistikus ini? Beranikah menerima jalan derita sebagai perjalanan batin, tempat jiwa ditempa dan dipurnakan? Jika ya, maka batu-batu dingin itu bukan lagi sekadar pahatan, melainkan ikon perjalanan menuju penyucian—jalan yang menyakitkan, namun juga satu-satunya jalan menuju keintiman terdalam dengan Yang Ilahi. *