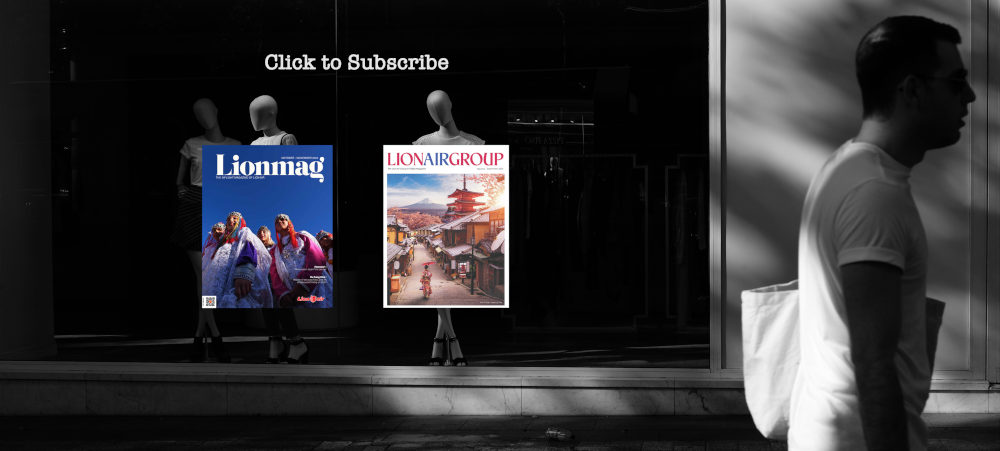Catatan dari Granada, Spanyol
Seorang perempuan bertubuh kurus muncul di tengah arena yang dikelilingi bule-bule lelaki perempuan.
Kakinya menghentak lantai, keras lalu melunak, seperti derap kuda yang berpacu lalu melambat.
Wajahnya menegang, kedua tangan berputar luwes, menyimpan tegangan yang tak bisa disembunyikan.
Di belakangnya, gitar dipetik dengan kegilaan nyaris tak terkendali, mengiringi nyanyian (seperti meratap dan marah) seorang penyanyi lelaki yang seakan mencabik-cabik isi ruangan kecil itu.
***
Dengan mata kepala sendiri aku menyaksikan apa yang terpampang di hadapanku bukan sekadar tari atau musik.
Lebih dari sekadar tari atau musik. Ia adalah letupan amarah, dendam, dan nestapa yang dipadatkan menjadi bahasa tubuh paling purba dan paling jujur: Flamenco.
Ya, flamenco, tarian yang sebagian besar kita di Indonesia mengenalnya sebagai tarian pengiring lagu.
Setidaknya, melalui lagu ‘Barcelona’ yang diciptanyanyikan oleh Faris RM. “gemerlap pesta kota, seolah getar flamenco mengalun jiwa,” demikian sebait lagu Faris RM.
Lagu ini memang menancap kuat dalam ingatan dan sanubariku.
Fariz bercerita Flamenco di Plaza Catalunya-Barcelona, tapi aku melihat Flamenco dimana tempat tarian ini dilahirkan, di Sacromonte Granada.
***
Aku mengunjungi Sacromonte untuk menyaksikan Flamenco secara langsung.
Memang ada banyak arena Flamenco di Sacromonte, tetapi pilihanku jatuh pada La Zambra María la Canastera.
María la Canestera adalah legenda Flamenco. Ia dikenal di seluruh dunia.
Rumahnya—adalah sebuah galian gunung berbentuk gua dengan langit-langit setengah bulatan mirip tapal kuda khas arsitektur Andalusia—menjadi arena menari yang telah dikunjungi presiden, tokoh-tokoh, ilmuwan dan para sosialita dari pelbagai belahan dunia.
Dibangun hampir 90 tahun lalu dan telah menjadi saksi bagaimana Flamenco bisa bertahan hingga hari ini.
***
Mengunjungi Sacromento untuk menyaksikan langsung tarian Flamenco tidak terjadi secara kebetulan.
Aku merencanakan jauh-jauh hari bahkan sebelum rencana mengunjungi Spanyol.
Tiket kupesan lebih sebulan sebelum datang. Itu pun dengan jatah masuk di jam yang belum jelas. Harga tiket 26 Euro/orang.
Di dalam gua Zambra María la Canastera udara gua terasa lembap, bercampur aroma kayu tua dan asap rokok.
Panci-panci tembaga berkilau redup diterpa cahaya lampu, seakan ikut menyimpan gema hentakan kaki yang memantul dari dinding batu.
Kursi-kursi kayu sederhana tersusun rapat membentuk setengah lingkaran, menempatkan penonton hanya sejengkal dari para penampil yang menari, menyanyi, dan memetik gitar di ujung ruangan.
Wajah-wajah penonton tampak terbius, sebagian mencondongkan tubuh, sebagian lain bertepuk tangan mengikuti irama.
***
Aku mengambil posisi duduk bagian dalam belakang yang searah pintu masuk dan persis depan pintu kamar tidur María sang legenda.
Gua ini penuh dengan foto para tokoh dan selebritas bersama María.
Aku duduk di salah satu sudut ruangan, di bawah deretan piring tembaga dan foto-foto klasik yang menggambarkan sejarah keluarga penari Flamenco.
Posisiku agak bersandar di kursi, dengan latar kain polkadot merah-putih yang khas. Aku tak paham bahasa yang didaraskan, tapi suara yang menyayat kuat bertingkah tingkah dengan lengkingan, membuat aku bisa merasakan kepedihan, ratapan, luka batin, kematian, cinta yang tak sampai, kesepian, dan nasib tragis.
***
Aku paham bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan hentakan-hentakan—yang membuat bibirku kering, nafas tersengal, jantung berdegup kencang, dan tak dinyana, ada air mata yang menetes.
Getir dan kepedihan itu menjalar menembus relung-relung gua dan sampai padaku yang duduk diam terpaku tanpa suara.
Flamenco berbicara dalam tiga bahasa yang tak terpisahkan. Cante (nyanyian) adalah jiwa, baile (tarian) adalah tubuh, dan toque (permainan gitar) adalah pikiran.
Ketiganya harus bersatu dalam harmoni yang sempurna.
***
Di dalam gua sempit itu, lantai batu bergema setiap kali kaki penari perempuan menghantamnya—keras, tajam, lalu tiba-tiba melunak seakan tersedak oleh kesedihan.
Tubuhnya berputar cepat, lalu membeku, kemudian kembali meledak dengan hentakan yang memaksa ruang bergidik.
Jari-jari gitaris memetik senar dengan kecepatanm yang ritmis, menghasilkan denting serak yang menusuk telinga dan dada, seolah setiap nada lahir dari luka yang tak pernah sembuh.
Dari sudut ruangan, suara penyanyi lelaki melengking panjang, serak, penuh getar, seperti jeritan seseorang yang kehilangan tanah, rumah, dan cintanya dalam satu waktu.
Suaranya naik-turun, memecah keheningan gua, mengaduk perasaan, membuat udara sesak oleh aroma getir penderitaan yang tak bisa diusir.
Di antara dentuman kaki, petikan gitar, dan lengkingan suara itu, aku merasa seakan-akan sedang menyaksikan kepiluan berabad-abad dijahit menjadi satu tarian, satu nyanyian, satu perlawanan yang tak kunjung padam.
***
Di pikiranku, di lubuk hati terdalam, memang pernah terbetik untuk suatu waktu dapat mengunjungi dan melihat tarian ini. Aku pernah membaca tentang sejarah Flamenco ini secara sekilas, tapi kemudian hilang begitu saja.
Ketika mendalami tentang 'nyeri’ dan derita dalam hidup manusia untuk kepentingan mengajar, secara tak sengaja, pikiranku terbawa pada Flamenco ini.
Flamenco memang lahir dan berkembang setelah penaklukan Andalusia (Reconquista, 1492), ketika Granada—benteng terakhir Islam di Spanyol—jatuh ke tangan Katolik.
Meskipun pematangan dan perkembangannya terus sepanjang ratusan tahun setelah itu.
Tarian itu melukiskan kepedihan dan nestapa, jeritan dan ratapan yang tak berkesudahan.
Flamenco sering dianggap sebagai gema sejarah traumatis Reconquista, sekaligus seni bertahan hidup bagi mereka yang tersisa.
***
Flamenco tidak lahir dari istana-istana megah Córdoba atau taman-taman Alhambra.
Ia lahir di jalanan berliku, di sudut-sudut gelap di mana orang-orang dengan latar belakang berbeda bertemu.
Lahir dari persilangan empat identitas besar usai penaklukan Andalusia—*Gitano* (gipsi), *Morisco* (Islam), Kristen, dan Yahudi—yang masing-masing menyumbangkan unsur khasnya.
Dari perkawinan jiwa-jiwa terbuang inilah Flamenco lahir. Melodi Arab—maqom, lengkingan, ritme siklis—yang syahdu berpadu dengan ritme Afrika yang menghentak, budaya Kristen Andalusia memberi ruang sosial prosesi religius yang menanamkan ekspresi doa publik dan menjadikannya seni pertunjukan terbuka. Puisi Yahudi, Ladino—tradisi liturgi penuh ratapan nan mendalam bercampur dengan tangisan Gitano yang memilukan.
Semua melebur dalam api kesengsaraan yang sama—kehilangan tanah air, kehilangan identitas, kehilangan cinta.
Percampuran ini memberikan nuansa spiritualitas kerinduan dan penderitaan, yang melahirkan konsep duende—jiwa penderitaan yang ditransformasikan menjadi kekuatan artistik.
***
Flamenco bukan sekadar musik dan tari. Ia adalah sintesis penderitaan kolektif dan ketangguhan spiritual dari masyarakat Andalusia yang pernah tercerai, tetapi tetap hidup dalam seni.
***
Cante jondo—nyanyian terdalam—adalah bahasa universal bagi para pendosa dan mereka yang terbuang.
Dalam soleá (nyanyian kesepian) yang melengking, bergema kerinduan akan tanah dan cinta yang hilang.
Dalam siguiriyas (nyanyian sarat kepedihan) yang mencekam, tersimpan kisah-kisah yang berakhir di tepi kematian.
Dalam saeta (nyanyian penuh doa) yang hening, doa-doa pun naik ke langit, lahir dari luka yang tak pernah kering.
Federico García Lorca (1898–1936), penyair Andalusia yang mati muda itu, pernah menulis tentang duende—jiwa misterius yang menghantui Flamenco autentik. “Duende bukanlah talenta,” tulisnya, “bukan pula kemampuan. Ia adalah api darah, ia adalah pergulatan dengan kematian.”
Dalam tradisi Gitano, duende hanya datang kepada mereka yang telah mengalami penderitaan sejati.
Ia tidak bisa dipelajari di akademi atau dibeli dengan uang.
Ia adalah hadiah dari para leluhur, warisan dari mereka yang telah menangis dalam kegelapan dan menemukan cahaya dalam tangisan itu sendiri.
Itu sebabnya, aku tak bisa menemukan resonansi manakala menyaksikan tarian ini di Jakarta maupun di Plaza Catalunya.
***
Apa yang terjadi di depan mataku bukan hanya pertunjukan malam itu.
Ia adalah gema sejarah berabad-abad: nestapa kaum yang terusir, kerinduan yang tak tersampaikan, dan doa yang lahir dari luka.
Flamenco, bagiku, bukan sekadar tarian Andalusia. Ia adalah jeritan purba manusia: ketika tanah dirampas, cinta direbut, dan identitas dihancurkan—yang tersisa hanyalah nyanyian dan hentakan kaki sebagai tanda bahwa jiwa ini be binasa.
BACA JUGA : Via Dolorosa a la Antonio Gaudi
Ketika malam turun di Andalusia, dan suara gitar Flamenco mengalun dari sebuah peña kecil di sudut kota tua, jiwa-jiwa yang lelah menemukan rumah mereka.
Di sanalah, dalam kegelapan yang diterangi hanya oleh cahaya lilin dan mata-mata yang berkobar, Flamenco terus menceritakan kisah abadi tentang cinta yang tak pernah menyerah, tentang harapan yang tak pernah padam, tentang jiwa manusia yang selalu mencari cara untuk bernyanyi meskipun dunia sedang menangis.
Bahkan ketika semua lampu gua dimatikan dan langkah kaki penonton perlahan menjauh, bau tembakau yang pekat, keringat yang menempel di kursi kayu, dan hawa pengap yang menyesakkan masih menggantung—seakan penderitaan itu enggan pergi, terus mengendap di udara, menunggu jiwa lain untuk merasakannya.(*)
* Taufiq F Pasiak, Contemplative Traveller