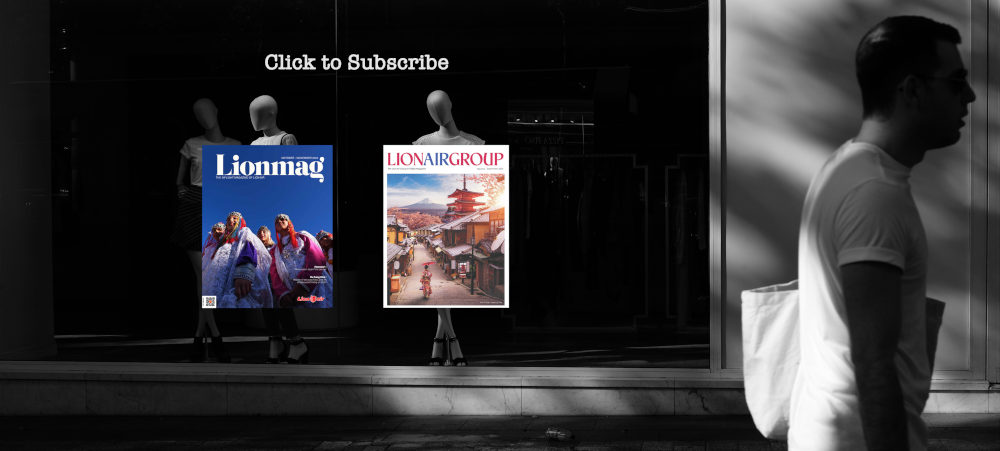OPINI
Oleh : JADD ABRAHAM
Dalam tatanan nilai universal, usia tua sering kali diletakkan di atas altar kehormatan. Ada sebuah ekspektasi kolektif bahwa seiring memutihnya rambut dan melambatnya langkah, seseorang akan mencapai apa yang disebut sebagai state of wisdom —sebuah kondisi di mana gejolak ego mereda dan berganti menjadi kearifan yang meneduhkan.
Namun, pada sosok Donald Trump yang akan menginjak usia 80 tahun Juni mendatang, hukum alam itu tampaknya mengalami anomali. Bukannya melahirkan ketenangan, senja usianya justru memicu kegaduhan yang kian absurd.
Paradoks usia dan akal sehat
Secara fisik, tanda-tanda kelemahan adalah niscaya. Manusia sehebat apapun ia berkuasa,tetaplah tak kuasa melawan waktu. Masalahnya bukan terletak pada fisik yang kian rapuh, melainkan pada akal sehat yang seolah ikut meluruh.
Alih-alih menjadi "ayah bangsa" yang menyatukan, Trump justru kian terjebak dalam labirin narsisme yang destruktif. Retorika yang ia lontarkan bukan lagi sekadar strategi politik, melainkan manifestasi dari kegilaan yang tak lagi memiliki batasan moral. Di saat seharusnya ia mewariskan stabilitas bagi generasi mendatang, ia justru sibuk menggali parit pemisah yang kian dalam.
"Setelah saya, banjir bandang”
Ada sebuah kekhawatiran yang beralasan: Trump tampaknya sedang menderita sindrom L’ etat, c’ est mori —negara adalah saya. Baginya, kejayaan Amerika Serikat hanya valid jika ia yang memegang kemudi.
Sadar atau tidak, tindakan-tindakannya mencerminkan sebuah keputusasaan eksistensial. Ia sadar bahwa riwayatnya di panggung dunia segera akan tamat. Namun, alih-alih keluar dengan kepala tegak dan meninggalkan warisan yang konstruktif, ia seolah ingin memastikan bahwa jika ia harus turun dari panggung, maka panggungnya pun harus ikut hancur. Ini adalah bentuk "prestasi" destruktif yang mengerikan: upaya untuk menyeret sebuah bangsa besar ke dalam jurang kehancuran bersama dirinya sendiri.
Keinginan terselubung untuk melihat AS "tamat" bersamanya adalah ancaman nyata bagi demokrasi. Ketika seorang pemimpin merasa dirinya lebih besar dari institusi, dan ketika kebencian dijadikan bahan bakar utama untuk tetap relevan, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekedar prestise dan reputasi diri, melainkan peradaban itu sendiri.
Dunia kini sedang menonton sebuah tragedi klasik yang dipentaskan di panggung megah. Trump bukan lagi sekadar politisi, melainkan pengingat pahit bahwa usia tua tanpa kearifan hanyalah kegilaan yang tertunda. Di tangan pemimpin yang merasa riwayatnya segera tamat dan tak lagi memiliki hari esok untuk dijaga, masa depan sebuah bangsa hanyalah sandera yang siap dikorbankan demi kepuasan ego di masa senja.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatatnya sebagai pejuang yang gagah berani, melainkan sebagai sosok yang ingin memadamkan lampu bagi semua orang, hanya karena lilinnya sendiri hampir habis terbakar.*****