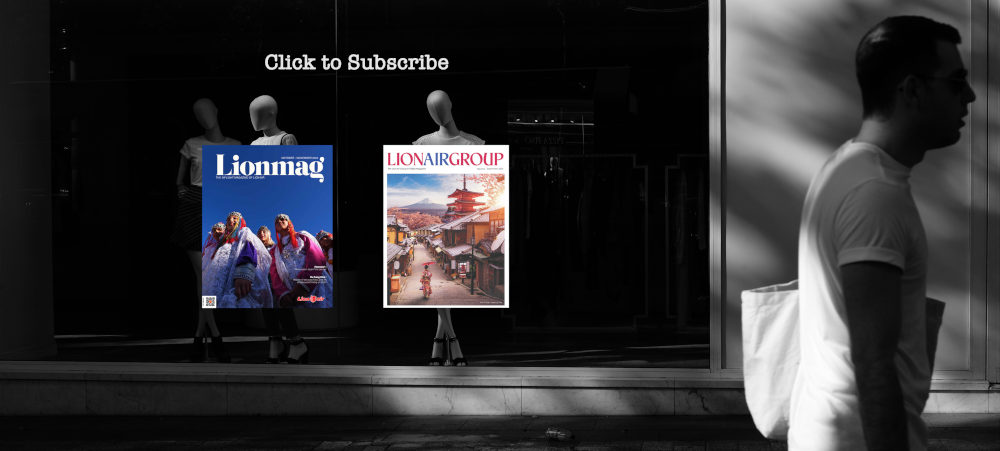Ibukota negara Laos yang minim polusi, tenang, dan menawan dalam suasana nan sederhana.
"Sabaidee…Ton sao…” sapa selamat pagi dari staf PVO Hostel, penginapan tempat saya bertetirah. Lae, nama staf itu, menyuguhkan Khao Piak Khao, sarapan mirip bubur bertabur daging.
“Anda dari Indonesia?,” tanyanya. Begitu saya mengangguk, Lae pun tersenyum, “berarti tidak perlu cemas soal makanan selama di Laos karena kami juga mengkonsumsi nasi dari sarapan hingga makan malam,” sambungnya.
Masih sekitar jam 06.00, tapi saya sudah siap memulai mengeksplor kota. Kebetulan PVO Hostel berjarak hanya beberapa ratus meter dari kuil Wat Sisaket. Saya berniat memotret suasana pagi di kuil tertua kota Vientiane tersebut, mengharap foto dengan efek sendu.
“Sebaiknya cepat-cepat kesana, karena jam begini ada ritual pemberian derma bagi para biksu,” Lae mewanti-wanti.
Serta merta saya pun bergegas ke Wat Sisaket. Memberi derma para biksu adalah tradisi harian penganut Buddha, umumnya dilakukan pagi-pagi. Para biksu yang berjubah jingga dan berkepala plontos berdiri di pinggir jalan masing-masing membawa tempat penampung derma semacam kendi bundar dari kuningan, lalu warga menyalami dengan santun dan menyodorkan pemberian mereka. Menyaksikan hal itu dalam atmosfer pagi yang syahdu terasa begitu menenteramkan hati.

Sekawanan bissu muda asyik membaca. Foto VALENTINO LUIS
Tidak hanya sebagai kuil tertua, Wat Sisaket juga memikat berkat arsitekturnya yang detail serta menampilkan lebih dari 2000 gambaran Sang Buddha. Karena pintu kunjungan baru dibuka jam 08.00 pagi, usai memotret para biksu saya terlebih dahulu beranjak sejenak ke tepi Sungai Mekong yang berada tak jauh, melewati Presidential Palace dan kuil Wat Ho Phra Keo. Disitu terdapat sebuah taman apik, Chao Anouvong Park, berapitan dengan pasar malam yang saya yakin bakalan elok didatangi saat senja.
Meskipun berposisi sebagai ibukota negara Laos, Vientiane tidaklah menampakan citra sebagai sebuah metropolitan. Hanya sedikit sekali bangunan tinggi, bahkan jarang saya temukan area perkantoran yang sibuk. Kota yang berdiri sejak abad 9 ini lebih menyerupai kota-kota propinsi di Indonesia, malah jumlah warganya tidak sampai 800,000 jiwa, masih jauh lebih rendah kepadatan penduduknya ketimbang Tasikmalaya, Malang, atau Bogor.
Lantaran bukanlah kota yang hiruk pikuk, sarana transportasinya pun standar saja. Kemana-mana mengandalkan bus umum berwarna hijau seukuran Damri atau menumpang Tuk tuk yang mereka sebut Jumbo. Pilihan lainnya adalah sepeda motor. Saya memilih yang terakhir ini karena lebih bebas dan praktis, kemanapun bepergian di Asia Tenggara, saya paling suka menyewa sepeda motor. Lae mendapatkan sepeda motor sewaan bertarif 100.000 Kip per hari atau Rp. 170.000.
Dari That Dam ke That Luang Thai
Kota yang tidak begitu padat dan jalanan yang jarang macet sangat membantu pengenalan geo-spasial bagi pendatang baru. Dalam waktu singkat saya bisa paham tata ruang Vientiane. Seolah-olah sudah pernah bermukim lama disini.
Mengandalkan sepeda motor, saya mendatangi titik-titik wisata utama entah kuil maupun monumen. Selain Wat Sisaket, yang terdekat dengan penginapan yakni That Dam, yang dikenal dengan sebutan Black Stupa. Lantas ada Patuxai Monument, hanya perlu 10 menit dari penginapan. Bangunan di tengah jalan ini ibarat Arch de Triumph-nya kota Vientiane. Berdiri tahun 1960-an, Patuxai Monument memang dibuat untuk mengenang para pahlawan yang gugur demi kemerdekaan Laos. Berlokasi di Lane Xang Avenue, didekorasi keemasan pada langit-langit. Pengunjung bisa naik ke bagian atasnya melewati tangga berbentuk spiral guna melihat panorama 3600 kota.
Dari sini, kemudian saya menempuh jalur ke timur kira-kira 10 menit dan mampir ke Pha That Luang, pagoda terpenting bagi umat Buddha Laos. Stupa emasnya sangat mencolok, yang diyakini penduduk sebagai simbol tulang dada Sang Sidharta Buddha Gautama yang dibawa oleh biksu utusan raja Asoka dari India untuk menyebarkan agama.
Pagoda ini dibangun pada masa pemerintahan raja Setthathirath pada tahun 1566. Saat mengitarinya, saya menemukan bahwa pagoda ini dikelilingi oleh biara para biksu dengan jendela-jendela yang kecil. Masuk ke dalam biara, terdapat banyak sekali benda-benda pra sejarah termasuk artifak purbakala. Kawasan Pha That Luang tidak semata hanya pagoda, tapi juga sejumlah bangunan menawan lainnya, juga taman yang rindang. Sejumlah pedagang kaki lima menjual es kopi susu yang nikmat, mereka membungkusnya dalam plastik laiknya di Indonesia kita membeli es cendol.
Melongok Buddha Park
Satu lagi situs yang signifikan dan jadi incaran banyak wisatawan di Vientiane adalah Buddha Park. Awalnya saya kira taman berisi patung-patung Buddha ini berada di tengah kota, namun ternyata saya musti cukup jauh mengejarnya ke luar kota, hampir satu jam berkendaraan. Untungnya, begitu keluar dari pusat kota, suasana pedesaan langsung terasa sehingga pejalan yang suka alam seperti saya langsung merasa terkonek dengan lanskap natural.
Buddha Park berada di Thanon Tha, desa di sebelah tenggara Vientiane, yang juga bersisian dengan Sungai Mekong. Saya tiba pas jam kunjung dibuka, dan rupanya sudah banyak orang juga yang telah menunggu. Tiket masuknya 50.000 Kit (Rp.85.000), dan ada tambahan biaya untuk pengguna kamera DLSR.
Taman ini ternyata tidak sebesar dugaan saya. Jika hanya mau sekadar melihat-lihat barangkali hanya 30 menit akan selesai. Namun kalau mau mengamati patungnya satu per satu secara detail dan memotret dari beberapa sisi, bisa lebih dari satu jam, apalagi jika datangnya tidak pas siang bolong. Lumayan, sebab ada lebih dari 200 patung Buddha dengan bermacam ukuran serta pose.
Dibuat 60 tahun silam, Buddha Park memiliki unsur Hindu yang kuat juga. Ini karena pendiri taman merupakan seorang biksu yang mempelajari kedua agama tersebut. Salah satu contoh elemen Hindu yakni patung Dewa Indra yang mengendarai gajah berkepala tiga. Bagian favorit untuk memotret yakni berdiri di atas patung labu raksasa dengan pintu berukir mulut setan setinggi 3 meter, mirip Goa Gajah di Bali.
Menjelang siang, saya kembali ke pusat kota. Lao menyarankan saya mendatangi National Ethnic Cultural Park yang juga berupa taman berisikan duplikasi rumah-rumah adat dari bermacam etnik Laos, seperti Taman Mini Indonesia Indah.
Sayangnya, saat saya tiba, tempat itu terkunci dan seakan tidak ada aktifitas. Saya memutuskan untuk pulang, beristirahat siang sejenak, karena sore nanti Lao akan membawa saya menumpang sampan keluarganya menyusuri sungai Mekong. Saya suka unsur-unsur kebersahajaan seperti ini yang merangkai tiap perjalanan.
Vientiane memang bukanlah kota besar yang canggih dan berdenyut riuh 24 jam, tapi siapa peduli? Tidak semua orang suka suasana demikian. Termasuk saya. (*)