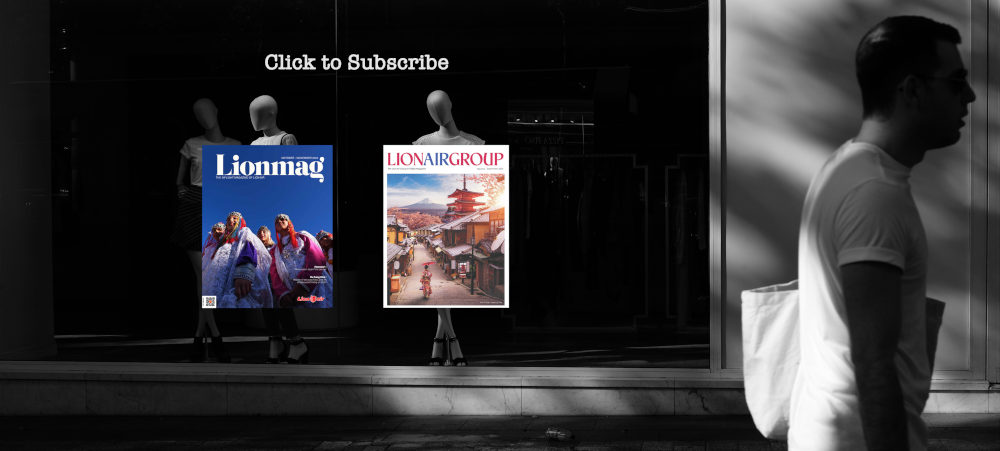RUMAH yang terletak di wilayah Jakarta Pusat itu amat sarat penghuninya. Luasnya tidak lebih 60 meter bujursangkar, sedangkan jumlah penghuni tetapnya tidak kurang 15 jiwa. Yang tergolong kanak-kanak sisa dua orang, selebihnya dewasa semua. Di antara mereka, tercatat tiga yang masih aktif sekolah, dua orang tua yang boleh dikatakan sudah uzur, empat orang yang secara bersama-sama atau bergantian merawat rumah dan memasak di dapur; lima orang penganggur tulen dan... hanya satu yang bekerja cari duit. Orang yang bekerja inilah yang membiayai rumah tangga secara keseluruhan, mulai dari pengadaan beras, lauk-pauk, membayar listrik dan air pipa, sampai membayar sampah dan membelikan rokok kepada lima orang penganggur itu. Hal ini saya anggap sungguh aneh. Jakarta yang begitu keras dan nafsi-nafsi itu masih memelihara seorang malaikat yang begitu ikhlas mengulurkan tangannya.
Mengapa saya katakan penganggur tulen? Kelima orang yang tampak fisiknya segar-bugar itu sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda malu atau berat hati terhadap orang yang membiayai hidupnya. Mereka kelihatan santai saja. Saban malam begadang, pagi sampai siang tidur pulas. Minum kopi digabung dengan makan siang sambil ngobrol tentang pengalaman semalam. Itulah kehidupan rutin mereka.
Di antara lima penganggur itu, terdapat dua orang kemanakan saya. Saya, yang saban berada di Jakarta harus singgah di rumah itu, selalu merasa terganggu melihat gaya hidup kemanakan-kemanakan yang amat keenakan sebagai parasit menghisap darah orang lain. Saya berusaha keras membongkar cara berpikir mereka. Berbagai jalan telah saya tempuh, tetapi belum ada tanda-tanda akan berhasil. Bahkan saya pernah menghamburkan kata-kata yang sedemikian rupa menghina sehingga membuat mereka menangis dan mengepal-ngepalkan tinju. Tetapi sampai di situ saja. Mereka tidak berani membantah atau melawan saya secara terbuka. Rupanya lembaga paman masih diperhitungkan, atau barangkali masih ada yang lain yang mereka khawatirkan, kondisi fisik saya misalnya. Kalau saya dibuatnya sampai marah betul, mungkin sekali gebrak saja, mereka bakal istirahat begadang beberapa malam!
*****
BARU-BARU ini saya menghadiri pertemuan besar pemimpin redaksi dan PWI se-Indonesia di Jakarta. Para peserta ditempatkan di hotel Sahid Jaya. Hotel ini terbilang mewah, berbintang lima. Sudah beberapa hari berada di kota "sepuluh juta jiwa" itu, namun belum terbuka kesempatan untuk menengok penganggur-penganggurku itu. Di dalam hati ini, mengental rasa kangen kepada mereka. Bagaimanapun mereka adalah anak kakak kandung saya. Sementara merencanakan mengatur waktu untuk menjenguk mereka, tiba-tiba pintu kamar diketuk orang. Begitu daun pintu terkuak, dua pasang tangan hampir bersamaan merangkul tubuh saya. Kami pun saling berangkulan sambil melangkah masuk dan masing-masing mengambil tempat duduk.

"Saya baru saja merencanakan menyiapkan waktu untuk menjumpai kalian, tahu-tahu kalian sudah muncul," saya memulai percakapan.
"Kami mengetahui kakak berada di Jakarta sejak tiga hari yang lalu. Kami lihat di layar televisi," salah seorang kemanakan memberi informasi. Kedua orang kemanakan saya itu sejak masih kanak-kanak memanggil saya "kakak". Ini mungkin karena mereka dibesarkan di lingkungan orang tua saya, tempat adik-adik memanggil saya begitu.
"Bagaimana kabar kalian?" saya meneruskan percakapan.
"Kami menemui kakak di larut malam ini, khusus untuk menyampaikan kabar gembira," salah seorang menyambut. Kalimat ini meluapkan ingin tahuku.
"Kabar gembira, alhamdulillah. Kabar gembira apa?" desakku tak sabaran lagi.
"Begini, Kak. Kritikan-kritikan, teguran-teguran, atau apa saja namanya, yang kakak lancarkan selama ini, sesungguhnya tidak berlalu begitu saja. Itu selalu menjadi bahan pemikiran dan renungan bagi kami. Dan pada saat inilah, kami ingin menyatakan sikap yang bakal menuntun langkah kami ke depan."
Kurang ajar, mereka makin menyesakkan nafas saya. Rasa ingin tahuku makin meluap-luap.
"Apa itu, apa itu. Cepat dong katakan!"
"Begini, Kak. Kami telah mengambil kata putus, mau jadi wartawan saja!"
*****
SUNGGUH, kata putus kedua kemanakan saya itu membuat saya betul-betul putus asa. Bukan hanya itu, di benak saya muncul macam-macam pikiran, tindih-menindih. Semua itu memuntahkan rasa jengkel, marah, kasihan, bercampur-baur tak karuan. Bayangkan. "Kami mau jadi wartawan saja." Dengan tambahan kata "saja" di akhir kalimat menandakan mereka menganggap enteng pekerjaan wartawan itu. Ini, sama halnya kalau kita bertamu di rumah seseorang dan tuan rumah menawarkan: "Mau minum apa?" Lantas kita jawab merendah: "Air putih saja". Jawaban ini menimbulkan kesan: jangan repot-repot, beri saja yang paling gampang, yang paling murah. Bahkan dengan menjawab "air putih saja" dapat diartikan "berikanlah sesuatu yang tidak perlu dibeli".
Alangkah kelirunya anggapan kemanakan-kemanakan saya itu. Saya sungguh dipaksa kembali untuk mengkhotbahi mereka. Bahwa untuk menjadi wartawan seperti Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, Jakob Oetama, Gunawan Mohamad (ini sekadar menyebut beberapa nama), itu sama sekali tidaklah gampang. Mereka ini begitu aktif berkomunikasi dan berdialog dengan dunia lewat berbagai bacaan, diskusi, seminar, dan macam-macam forum lainnya. Tidak ada majalah, tidak ada berita penting yang boleh terbit dan lewat begitu saja tanpa mereka lalap. Mereka menyatu dalam degup jantungnya "jagat raya" kemanusiaan.
"Maaf, kemanakan-kemanakanku. Saya ingin berterus terang untuk yang terakhir kalinya. Jangan mimpi untuk menjadi wartawan. Bakat dan modal-dasarmu amat kurang untuk tidak dikatakan kosong sama sekali. Saya tahu persis siapa kalian. Jadi, carilah pekerjaan yang halal dan cocok dengan kemampuanmu. Bagaimana kalau saya memberi modal untuk membeli sebuah gerobak dan kalian menjual gado-gado saja?"
Mereka diam. Kami bertiga diam.
Waktu menunjukkan pukul dua dini hari. Dengan langkah gontai, tanpa semangat, tanpa salam apa-apa, mereka meninggalkan kamar. Mata saya tak terpejam, terasa gatal dan perih. Hati ini sedih. Barangkali mulut ini terlalu lancang, terlalu berterus terang. Mentang-mentang berhadapan dengan kemanakan sendiri, tak mengindahkan lagi tenggang rasa.*****