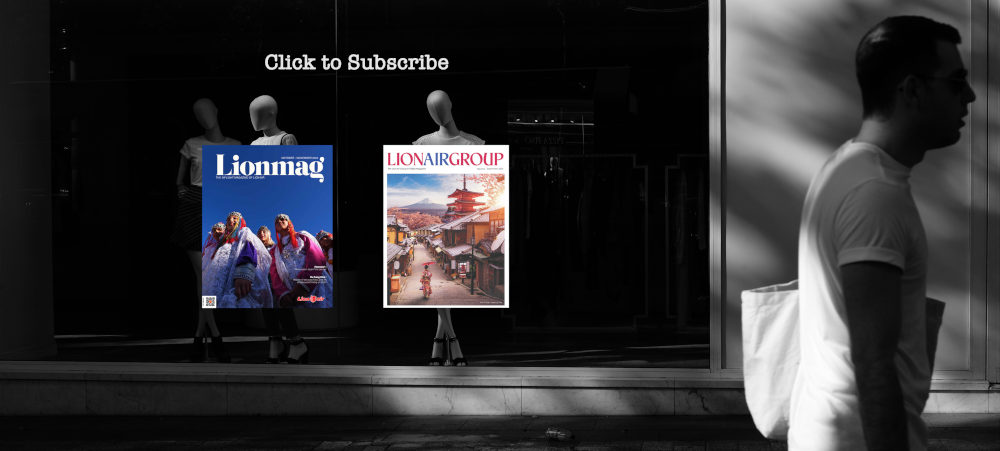Dari ruang-ruang komunitas hingga istana budaya, dari legenda kuno sampai kegelisahan usia dua puluh-an, dunia teater Indonesia terus bergerak, bereksperimen, dan menjangkau generasi baru.
Tahun ini, sederet kelompok dan komunitas menghadirkan pementasan yang berbeda rupa, warna, dan energi dalam Festival Musikal Indonesia 2025 sepanjang akhir pekan kemarin. Masing-masing datang dengan latar unik, namun semuanya berbagi semangat yang sama: merayakan seni pertunjukan sebagai ruang ekspresi, refleksi, sekaligus menyuarakan identitas.
Adalah Jakarta Art House (2019) membuka hari dengan cerita dari usia dua puluh-an. Komunitas seni pertunjukan yang inklusif ini menghadirkan pementasan bertajuk ‘Rumah Pikiran dan Hati’ yang mengangkat isu menghadapi quarter-life crisis. Musikal ini berkisah tentang eksplorasi rasa dan kebingungan khas usia dua puluhan.

Berkolaborasi dengan komunitas In Our Twenties, musikal ini mengembangkan cerita orisinal menjadi pengalaman panggung yang penuh lagu baru dan desain visual yang mencerminkan proses tumbuh dewasa. Yang tidak pasti, kadang kacau, namun selalu jujur.
Bumi Bajra (-) menggarap pementasan yang meleburkan energi tari, taksu, dan spirit perempuan. Terlahir dari kesadaran untuk menjaga nilai-nilai luhur melalui tubuh, suara, dan gerak, komunitas ini menghadirkan seni sebagai ritual jiwa. Di sini, tari bukan sekadar hapalan gerak, tetapi perjalanan menuju taksu—energi hidup dalam sebuah karya.
Bagi Bumi Bajra, eksperimen dan tradisi berjalan berdampingan, dilatari suara alam dan kehidupan desa.
Musikal berjudul ‘Hyang Ratih – Ode untuk Bulan, Perempuan, dan Semesta’ terinspirasi dari mitologi Bali tentang Dewi Bulan yaitu Dewi Ratih dan Kala Rau. Karya ini ditata ulang melalui musik, tari, dan teater kontemporer. Panggungnya menjadi ruang refleksi akan perempuan, spiritualitas, relasi manusia dengan alam, juga krisis identitas budaya yang dihadapi generasi kini.
Sosok Karna, kesetiaan, dan dharma menjadi isu krusial yang diangkat Swargaloka dalam musikal mereka. Bertajuk ‘Panah Matahari – Adipati Karna’, pementasan ini mengisahkan perjalanan hidup Karna, anak dewa yang dibuang dan tumbuh sebagai kesatria yang selalu direndahkan karena status sosialnya.
Ketika perang Bharatayuda pecah, Karna memilih berpihak pada Kurawa demi membalas budi, meski ia tahu kebenaran berada di sisi Pandawa. Cerita ini menjadi ruang empati bagi siapa pun yang pernah merasa tersisihkan, namun tetap memilih setia.
Swargaloka (1993) ‘lahir’ dari pasangan seniman Suryandoro dan Dewi Sulastri. Keduanya mendirikan kelompok ini untuk mengeksplorasi seni pertunjukan berbasis budaya lokal. Salah satu cirinya adalah drayang—drama musikal wayang yang telah mereka pentaskan sejak 1998.
Ketika Tubuh Menjadi Protes
Berdiri pada 2017 oleh kolaborasi dua seniman—Dian Bokir dari Indonesia dan Martina Feiertag dari Jerman—Dimar Dance Theatre menggabungkan teknik tari modern Eropa dengan akar tradisi Asia. Hasilnya adalah karya-karya yang intens, eksperimental, dan sering kali menggugah kegelisahan sosial.
Dalam Festival Musikal Indonesia 2025, kelompok teater ini menghadirkan pementasan bertajuk ‘Ritus Negeri Celeng’. Lakon ini merupakan sebuah karya provokatif tentang keluarga, naluri bertahan hidup, dan manusia yang bisa menjadi lebih ‘celeng’ dari celeng itu sendiri. Terutama ketika nurani dikalahkan oleh ego.
Lewat metafora yang tajam, karya ini menggugat keserakahan, kehancuran moral, dan kehampaan empati.