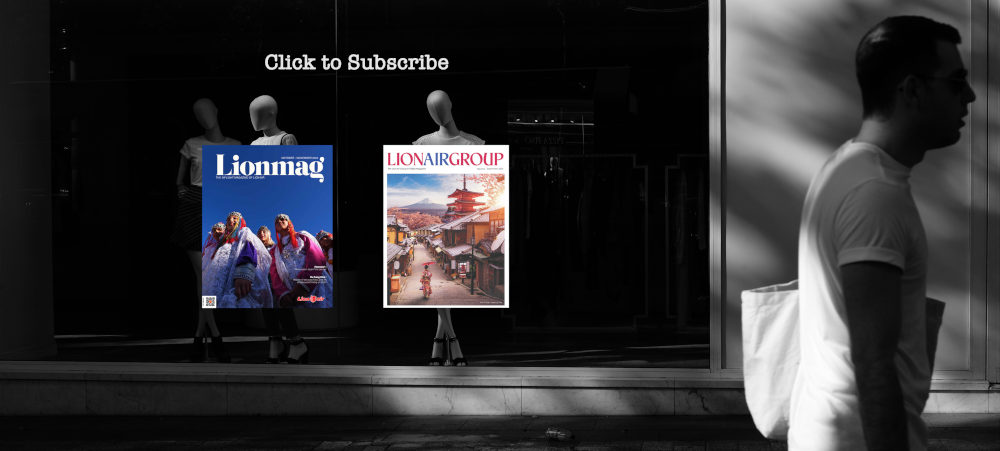Berhari-hari mencari jejak pesut mahakam, yang saya dapatkan malah permata lain yang tak kalah eksotis.
Akhirnya kami berlabuh juga di sebuah dermaga kayu, di dekat sebuah toliet terapung, di sisi barat pelabuhan Melak. Kota kecil yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ini merupakan salah satu pelabuhan persinggahan yang cukup ramai di tepi Sungai Mahakam.
Sejak pagi saya bersama Syachraini, dan jurumudi Acong, menyusuri Sungai Mahakam ini dari Muara Pahu, basecamp kami yang berjarak 4 jam perjalanan dari Melak, ke arah hilir (timur). Kami tengah mencari pesut (Orcaella brevirostris), mamalia air mirip lumba-lumba yang langka dan hanya hidup di Sungai Mahakam. Sudah lama saya ingin tahu bagaimana nasib mamalia ini, terlebih dengan semakin ramainya aktivitas penambangan batubara di Kalimantan Timur, yang menggunakan Sungai Mahakam sebagai jalur utama transportasinya.
Menurut penelitian Yayasan Konservasi-Rare Aquatics Species of Indonesia (YK-RASI) –Syachraini bekerja sebagai ketua monitoring pesut– suara deru mesin dari perahu angkutan penumpang saja bisa ‘mengusir’ pesut dari jarak 250 meter. “Apalagi suara mesin kapal tongkang penarik batubara, bisa mengusir pesut dari jarak 500 meter,” tutur pria yang sudah bekerja di YK-RASI sejak tahun 2003 itu.

Dengan semakin ramainya Sungai Mahakam ini oleh hilir mudik perahu dan kapal, berarti makin terusik pula ketenangan habitat pesut, dan membuat mereka mencari tempat yang lebih tenang dan terpencil, di cabang-cabang Sungai Mahakam. Salah satunya adalah Sungai Kedang Pahu, yang di muara pertemuannya dengan Sungai Mahakam terletak sebuah kota kecil Muara Pahu, yang menjadi pusat monitoring pesut. Masalahnya, jumlah anak-anak sungai ini tak hanya satu atau beberapa, tapi puluhan. Sementara, panjang Sungai Mahakam sendiri mencapai 920 kilometer! Jadi, mencari pesut yang tengah berenang-renang di sungai sambil sesekali menyemprotkan air itu ibarat mencari sebatang jarum di tumpukan jerami.
Sekarang ini, menemukan beberapa pesut saat melakukan monitoring itu sudah sangat beruntung. “Itu juga kalau surveinya berminggu-minggu,” tutur pria berbadan jangkung ini.
Yang ketiban sial justru saya. Sudah tiga hari tinggal di Muara Pahu, dan berperahu mencari pesut dari pagi hingga sore, tidak ada satu pun yang saya jumpai. Dua hari yang lalu kami menyusuri sungai hingga ke Muara Boloan –salah satu anak sungai Kedang Pahu– namun yang kami temukan hanya bekantan, primata lucu berhidung besar yang tengah asyik makan di pohon di pinggir sungai.
Kemarin, kami berperahu ke hilir hingga ke kota Penyinggahan, 2 jam ke timur dari Muara Pahu. Dari sini kami masuk ke Danau Jempang, salah satu dari tiga danau besar yang letaknya tak jauh dari Sungai Mahakam. Dua danau lain adalah Danau Sebayang dan Danau Melintang. Namun harapan kami tak kesampaian juga, karena ternyata danau seluas 15.000 hektar ini dangkal sekali, hanya sedalam lutut!
“Agar bisa berenang, pesut butuh kedalaman minimal tiga meter,” tutur Syachraini. Terang saja, dengan kedalaman hanya setengah meter, tak akan ada pesut masuk ke danau ini, takut kalau-kalau nantinya 'kandas' dan akhirnya mati. Hiburan kami yang ada adalah berjenis-jenis burung yang mendiami danau ini, serta sebuah perkampungan nelayan. Beberapa wanita tengah mengelompok di ujung perkampungan, menyortir ikan-ikan hasil tangkapan suami mereka, untuk dijadikan ikan kering.
Lelah, petang dan malam saya habiskan untuk nongkrong di kantor YK-RASI, sebuah kantor terapung berdinding kayu yang ada di tepi Sungai Mahakam, tak jauh dari muara Sungai Kedang Pahu. Kantor ini, bersama rumah-rumah lain yang didirikan di pinggir sungai –termasuk rumah Acong– distabilkan dengan batangan-batangan kayu besar atau drum-drum kosong di bawah lantainya, dan diikat dengan tali baja ke daratan di pinggir sungai. Karena tidak berpondasi, maka ketika ada perahu atau tongkang lewat, rumah pun bergoyang-goyang. Jika air pasang ataupun surut, panjang tali pengikat pun mesti disesuaikan agar rumah tidak hanyut atau kandas. “Rumah beserta isinya dengan mudah kami pindahkan dengan mendorongnya memakai tangan saja,” senyum Acong.
Lagi-lagi, sampai saya tertidur, tidak ada tanda-tanda pesut yang lewat. Tentu saja, mereka bisa lewat ketika saya tengah tertidur. Toh pesut-pesut itu tidak terpaku pada jadwal tertentu seperti kereta api atau pesawat terbang!
Akhirnya, pagi ini, kami memutuskan untuk mencari pesut dengan menyusuri Sugai Mahakam ke arah hulu, ke Melak. Dan, ya Tuhan, ternyata menyusuri Sungai Mahakam dengan perahu tempel yang lebarnya cuma cukup untuk duduk satu orang ini mendebarkan sekali. Terlebih, sungai ini besar dan ramai dengan lalu lintas perahu dan kapal besar. Apalagi, saya kurang pandai berenang, dan tidak ada jaket pelampung di perahu! Kalau berpapasan dengan kapal angkutan penumpang –orang sini menyeburnya ‘taksi air’– riak airnya cukup untuk menimbulkan gelombang yang jika ditabrak perahu kami, rasanya seperti tengah naik mobil yang menabrak tiga lubang jalan berturut-turut.
Kalau perahu kami berpapasan dengan kapal tongkang penarik batubara, maka meskipun kecepatan tongkang itu lebih lambat, namun karena ukurannya jauh lebih besar, gelombang yang ditimbulkannya membuat perahu kami bergoyang ke kiri-kanan dan air sungai muncrat ke dalam perahu. Acong akan menghentikan perahu sebentar, sementara saya dan Syachraini berpegangan pada kedua sisi perahu agar tidak tercebur ke sungai.
Lebih khawatir lagi kalau hujan deras. Rasanya perahu kami kurang sekali memberkan perlindungan dari curah hujan. Sewaktu mendekati Melak tadi, di depan kami mendung tebal, dan gerimis mulai turun. Hati saya mulai kecut. Tadinya saya mau menyarankan Acong untuk menepi sebentar, meskipun di kanan-kiri sungai tidak ada perkampungan. Namun setelah beberapa menit, gerimis berhenti dan awan hitam pun bergerak menjauh. Syukurlah!
Rencana Cadangan
Sampai mendarat di dermaga pelabuhan Melak, tak ada satu pun pesut yang kami temui. Saya merasa hopeless. Terus apa yang bisa saya tulis dari perjalanan ini?
Eh, ternyata Syachraini punya sebuah ‘rencana cadangan’. “Bagaimana kalau kita mampir dulu ke hutan konservasi anggrek hitam di Kersik Luway, sekitar 15 km selatan Melak ini? Tadi malam saya sudah menelepon penjaganya, katanya ada anggrek yang sedang mekar.”
Heh, rupanya dia sudah menyiapkan rencana cadangan itu dengan baik, bahkan di luar perkiraan saya. Sebab begitu kami merapat di Melak, seorang temannya datang dan meminjamkan sepeda motor bebeknya untuk kami pakai.
Kami pun melaju melewati pasar, lalu pusat kota, lalu berbelok ke selatan. Saya sedikit surprised mengetahui bahwa di Melak, pedalaman Kalimantan Timur sekitar 350 km dari Samarinda, jalan-jalan utama sudah lebar dan diaspal dengan halus. Menara-menara penguat sinyal handphone berdiri di beberapa tempat sehingga tak perlu khawatir dengan masalah komunikasi.
Setelah melewati pedesaan dan rumah-rumah panggung di kiri-kanan jalan, kami melalui jalan yang agak naik-turun, dan begitu jalan utama berbelok ke kanan, kami mengambil jalan yang lurus, yang menjadi jalan masuk ke hutan konservasi Kersik Luway. Kini jalan berubah menjadi jalan batu kapur warna krem, dengan pohon-pohon karet yang cukup rapat di kiri-kanan. Saat musim kemarau, jalan ini cukup keras sehingga mudah dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Anggrek Hitam Kalimantan (Coelogyne pandurata) merupakan satu dari enam jenis anggrek yang masuk dalam genus Coelogyne. Anggrek ini merupakan tanaman endemik di Kalimantan, dan terdapat juga di Nepal, Cina, Filipina, Papua, hingga Kepulauan Pasifik. Di Kalimantan, anggrek ini bisa ditemui di berbagai tempat, namun lokasinya tidak selalu mudah dicapai. Hutan konservasi Kersik Luway ini lokasi yang paling mudah dikunjungi.
Didimus, salah seorang petugas hutan konservasi dan juga staf BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, menyambut kami di pos pengawasan hutan. Setiap hari ada dua staf yang bertugas di tempat yang sepi ini. Selain menjaga hutan, mereka juga mengantarkan tamu yang datang. “Tidak banyak, tapi ada tamu yang ke sini, umumnya turis dari Eropa,” tutur Didi.
Jalanan menuju lokasi anggrek ini memberi kejutan lain, karena ternyata berupa pasir putih yang halus. Cocok sekali dengan nama ‘kersik luway’, yang artinya ‘pasir sunyi’. Dengan pohon-pohon yang tampak seperti pohon bakau, orang bisa saja mengira hutan ini terletak di tepi pantai.
Menurut Didi, tanah berpasir putih ini hanya terdapat di lingkungan hutan di mana tumbuh anggrek hitam, kira-kira seluas 17,5 hektar. Di bagian lain hutan konservasi yang luas keseluruhannya 5.000 hektar ini tanahnya berpasir hitam. Hutannya bukan hutan dengan pohon-pohon kayu besar dan tinggi, melainkan hutan karangas yang pepohonannya berbatang kecil dan rendah, paling tinggi sekitar empat meter. Yang banyak terdapat di sini adalah pohon berengganyi, favorit anggrek hitam untuk menempel tumbuh. Batang pohonnya tak lebih besar dari lengan orang dewasa, pucuk daunnya berwarna merah menyala, yang berubah menjadi hijau lalu kuning ketika menua. Buahnya kecil-kecil kuning, berubah menjadi hitam saat masak dan manis. Lalu ada pohon pelawan yang berkayu merah, serta pohon uwai yang berkayu hitam dan berukuran lebih besar. Tak ketinggalan tanaman suplir dan pakis, serta kantung semar (Nepenthes sp.). Nampaknya, Kersik Luway juga menjadi surga tanaman pemakan serangga ini, karena saya menemui berbagai warna kantung semar bergelantungan di pohon maupun berserakan di atas tanah.
Baru lima menit berjalan, kami masuk ke rimbunan pohon, dan mulailah terasa lebih sejuk. Beberapa kali kaki kami amblas karena tanah yang kami injak gembur oleh humus yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Hutan ini pernah terbakar tahun 1982, 1987, dan 1997, namun untungnya tidak memusnahkan spesies-spesies anggrek di sini.

Segera kami menjumpai tanaman anggrek hitam yang pertama, yang belum berbunga. Pohonnya menggerombol di atas humus, di permukaan tanah, di antara pohon-pohon berengganyi. Batang pohon anggreknya yang berwarna hijau muda berbentuk seperti umbi yang pipih dan berakar serabut. Daunnya lebar dan panjang seperti daun palem. Bakal bunga muncul dari pangkal pohon dekat akar, yang lalu tumbuh menjadi batang berwarna hijau muda dan memunculkan 6-10 kuntum bunga.
Menurut Didimus, perlu waktu sekitar empat minggu dari mulai muncul tunas bunga hingga menjadi bunga yang mekar. “Anggrek ini bisa berbunga kapan saja, namun yang paling banyak di bulan Desember,” terang Didi, yang telah bertugas di sini sejak tahun 1996.
Selain anggrek hitam, kami menemukan beberapa jenis anggrek lain. Ada anggrek tebu yang tinggi dan mirip pohon tebu, anggrek anyaman, anggrek tajuk tuan, dan anggrek kipas. “Ada juga anggrek merpati, buluh rindu, manuntung, kumis kucing, anggrek bulu landak, semuanya ada 57 jenis anggrek,” jelas Didi.
Hutan ini rimbun oleh pohon namun di banyak bagian terdapat jalan-jalan setapak yang berpasir putih. Saya menjumpai anggrek hitam yang tengah berbunga begitu Didi menyibakkan gerumbul daun-daun dari pohon di pinggir sebuah jalan setapak. Dan… surprise!
Tadinya saya mengira, anggrek ini keseluruhan bunganya berwarna hitam. Ternyata tidak. Satu tangkai bunga anggrek ini, yang terdiri tiga kuntum yang sudah mekar dan tiga lainnya masih kuncup, tiap kuntumnya memiliki lima helai petal berwarna hijau muda. Bentuknya mirip petal bunga kenanga. Di pangkal petal terdapat mahkota bunga berbentuk seperti mangkuk, dengan urat-uratnya yang berwarna hitam, mewadahi kepala putik. Uniknya, mangkuk ini punya lidah panjang yang berwarna hitam, dengan hiasan bintil-bintil hijau muda yang sepertinya tempat serbuk sari.
Saya ‘syok’ oleh warna hitam yang menyelimuti bagian tengah lidah bunga. Jika diperhatikan lebih dekat, hitamnya tidak seperti satu lapisan saja, melainkan seperti tumpukan jelaga knalpot mobil yang lama tidak dibersihkan. Sementara di bagian pinggirnya penuh hiasan ‘tato’ warna hitam. Nampaknya, berbeda dengan anggrek lain yang menonjolkan kecantikan warnanya, anggrek ini ingin menonjolkan eksotika struktur lidah hitamnya itu. Kalau Didimus tidak bilang masih ada tiga tangkai lain yang sedang mekar, saya pasti akan berlama-lama memotret anggrek ini.
Anggrek hitam kedua terdiri dari tiga kuntum yang sudah mekar, dan dua lainnya masih kuncup. Memperhatikan anggrek ini, mendadak saya menyadari satu hal lagi. Ternyata, mulai dari bagian ujung lidah hingga mangkuk putik, serta lima petal bunga, kalau ditarik garis vertikal di tengah, akan membentuk simetris kiri-kanan. Kata Didimus, kalau banyak terkena sinar matahari, dalam tiga hari bunga akan layu. “Tapi kalau terlindungi pohon-pohon lain, bunga yang telah mekar bisa bertahan hingga seminggu.”
Kami melewati dua kuntum anggrek hitam yang masih kuncup, lalu Didimus menyibakkan daun-daun berengganyi. Lagi-lagi saya menemukan setangkai anggrek hitam! Kali ini kira-kira panjangnya 50 sentimeter. Baik yang telah mekar maupun yang masih kuncup masing-masing berjumlah empat kuntum. Yang menguntungkan dari anggrek-anggrek hitam ini adalah, tumbuhnya tak terlalu tinggi dari permukan tanah, sehingga saya tak kesulitan memotretnya.
Anggrek hitam keempat tampaknya seperti menjadi pemuncak, karena kedelapan kuntumnya tengah mekar semua! Yang menarik, kuntum sisi kiri berjumlah lima, sementara yang sisi kanan berjumlah tiga. Menurut Didi, saat mekar penuh, anggrek hitam ini mengeluarkan bau wangi. Begitu saya mencium anggrek itu, sulit saya mendeskripsikan wanginya. Wanginya terasa samar, lembut, seperti wangi parfum yang mahal.
Kami melewati lagi anggrek hitam yang sudah layu, lalu Didi mendapati satu kuntum anggrek tajuk tuan yang belum mekar. Saya menjumpai beberapa pohon pakis yang berbintik-bintik. Jalan yang kami lalui ini ternyata mengarah lagi ke jalan setapak waktu kami masuk tadi. Jadi tur kami sudah selesai! Hanya sekitar satu setengah jam, namun sangat mengesankan.
Kami pamit ke Didimus dan Pak Torung yang akan menggantikannya jaga, lalu kami kembali ke Melak, untuk meneruskan pencarian pesut hingga ke Muara Pahu. Namun kali ini, menemukan pesut atau tidak, saya tak begitu khawatir lagi, karena saya sudah menemukan penggantinya yang sepadan.