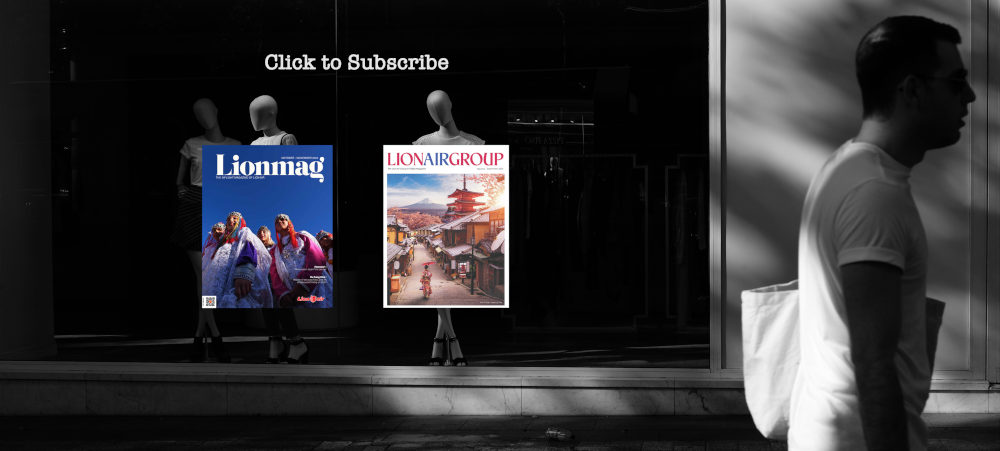Samudera sebening kaca, embusan angin laut, dan segar udara pegunungan akan selalu mengingatkan saya pada pesona “negeri bahari”, Kepulauan Togean. Dunia bawah laut yang kaya terumbu karang dan biota dasar perairan bisa saya nikmati meski sekejap, tetapi kesannya begitu mendalam.
Text dan Photo : Bayu Indra Kahuripan
Perjalanan dari Jakarta ke Ampana jauh lebih lama ketimbang yang saya perkirakan. Bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pukul 05.00 WIB, pesawat yang membawa saya mendarat di Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie, Palu, sekitar pukul 08.00 WITA.
Berniat mengejar penerbangan lanjutan dari Palu ke Ampana, tetapi pagi itu pesawat berangkat lebih cepat. Saya pun memutuskan menempuh perjalanan darat dengan minibus. Dari Ibu Kota Sulawesi Tengah itu, butuh waktu sekira delapan jam menuju Ampana, kota bahari berjarak 365 km. Dengan tarif Rp 150 ribu, sopir pun mengantarkan setiap penumpang sampai tujuan masing-masing.
Menumpang minibus retro bercat kuning bersama tujuh kawan seperjalanan memang terasa cukup lama, tapi tak sedikit pun kebosanan hinggap. Sopir sengaja membiarkan jendela minibus terbuka. Sepanjang jalur yang diapit bukit dan pantai, embusan angin menyerbu masuk. Kami menghirup udara segar kala melewati bukit dan pegunungan yang menawarkan pesona luar biasa.

Kami singgah sebentar di Parigi untuk makan pagi-setengah siang. Harum aroma laut dan ikan bakar meruak sampai tertangkap dua lubang hidung, bahkan sebelum kami turun dari minibus dan melangkah masuk salah satu rumah makan.
Dalam sekejap, terhidang di depan kami sepiring nasi hangat, selepek sayur kangkung, setengah mangkuk kuah asam, dan tentu saja sang juara, ikan bobara rica-rica. Sambal berupa cabai yang dipotong kecil-kecil, irisan halus tomat dan bawang merah, dibalurkan pada ikan.
Pedas luar biasa, tapi tidak “berat” di lidah. Sebaliknya, terasa segar ketika menyantapnya sembari menyeruput sesendok kuah asam. Pas dengan gurih ikan dan oseng kangkung.
Kami baru tiba di Ampana selepas petang. Saya memilih beristirahat di sebuah hotel kecil di Tanjung Lawaka yang tak jauh dari Pelabuhan Ampana. Kota ini merupakan kecamatan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una.
Setelah beristirahat semalamam, saya bergegas menuju Pelabuhan Ampana untuk menyeberang ke Kepulauan Togean dengan feri. Beberapa teman dari Palu sudah menunggu di dermaga.
Kami memilih rute langsung tujuan Pulau Papan karena ongkos perjalanannya lebih murah ketimbang harus terlebih dulu transit di Wakai. Tiket kapal cepat itu hanya Rp 95 ribu. Waktu menunjukkan pukul 09.30 WITA ketika kapal mengangkat sauh dan perlahan bergerak meninggalkan Ampana.
Selama perjalanan menuju Pulau Papan, tersaji pemandangan laut biru yang bening, dengan gugusan Kepulauan Togean yang ditumbuhi banyak pohon kelapa dan bakau (mangrove). Beberapa kali kapal kami bersandar di berbagai titik. Salah satunya, Kabalutan, sebuah desa di kecamatan Walea-kepulauan.
Menepi sebentar di Kabalutan, kami disambut keramahan anak-anak suku Bajau yang bermain dengan perahu ketinting mereka di sekitar dermaga. Kabalutan merupakan area berpenduduk terpadat di Kepulauan Togean.
Perjalanan kemudian berlanjut ke Pulau Malenge. Pulau besar ini merupakan persinggahan terakhir sebelum kapal menjatuhkan jangkar di laut tepian Pulau Papan yang begitu transparan. Sebening kaca. Tak lebih dari enam jam, asa menengok kehidupan masyarakat asli pulau nan elok itu pun terwujud.
Penduduk dengan ramah melempar senyum kepada kami yang datang. Sementara anak-anak sibuk berenang dan bermain di seputaran dermaga kecil pulau itu. Beruntung, kami diperbolehkan beristirahat dan menginap di salah satu rumah warga di pulau.
Hari Minggu di Pulau Papan. Sebagian besar warga yang berprofesi sebagai nelayan sedang libur melaut. Namun, berkat momen itu, kami justru bertemu banyak warga dengan ragam aktivitas di pulau. Anak-anak pulau berenang dan menyelam, sebagian bermain layang-layang di bukit batu dan karang.
Warga yang menyambung hidup sebagai perajin tikar ombori, menganyam daun pandan yang diimpor dari Pulau Malenge. Pulau ini terletak tepat di sebelah Pulau Papan. Daun pandan beruas besar itu diangkut menggunakan perahu ketinting, alat transportasi utama penduduk di negeri kepulauan.
Pulau Papan memiliki pemandangan senja yang berbeda. Kala sore menjelang, berdiri di atas jembatan sepanjang 1 km yang menjadi identitas pulau ini merupakan momen tak terlupakan. Dari sini, saya tenggelam dalam pesona matahari terbenam yang sangat indah.
Semburat warna merah muda teregradasi biru langit terang cemerlang. Ketika cahaya jingga mentari senja mulai lenyap di ujung samudera, sore berganti petang. Malam tiba menandai aktivitas warga berhenti total. Semua beristirahat. Beberapa lelaki terlihat duduk santai di depan pintu atau teras rumah panggung yang “mengapung” sambil mengobrol.
Keesokan paginya, saya tak sabar menyeberang ke pulau lain untuk melihat pemandangan berbeda di desa yang penduduknya bermata pencaharian sebagai pembuat gula aren. Saya diantar warga Pulau Papan bernama Pak Sahar menuju Desa Baulu. Kami menumpang perahu ketinting miliknya. Meski masih berada di wilayah Kepulauan Togean, perlu waktu sekira dua jam dari Pulau Papan ke Desa Baulu.
Sampai di Desa Baulu, saya bertemu tiga pemuda lokal yang kebetulan sedang mencari getah aren untuk dimasak menjadi gula merah. Ardi, Egi, dan Fadhlan, biasanya menelusur jejak getah aren di bukit belakang rumah mereka.

Tak pernah ada kata lelah dari tiga kawan baru saya saat harus berjalan kaki menempuh jarak lebih dari 3 km untuk mengumpulkan getah aren. Masing-masing melangkah sambil memanggul sebilah bambu besar setinggi tubuh mereka (sekira 1,5 meter) yang berfungsi sebagai wadah. Bila terkumpul penuh, mereka membawa getah aren itu pulang.
Memasak getah aren hingga menjadi gula merah memerlukan waktu sekira lima jam.
Aren dan mengolah getahnya bukan satu-satunya sumber penghidupan masyarakat Desa Baulu. Sebagian lainnya memilih bercocok tanam, sebagai petani perkebunan cokelat dan cengkih. Hasil kebun mereka—beserta produk turunannya—biasa didistribusikan ke pulau-pulau terdekat atau daerah di sekitarnya, seperti Togean, Ampana, dan Palu.
Sebenarnya saya tidak puas sekadar melihat proses pembuatan gula aren. Tapi, saya dan Pak Sahar harus kembali ke Pulau Papan sebelum petang sebab air mulai pasang dan semakin sore, angin bertiup lebih kencang. Apalagi, rute kami pulang “menantang” angin datang.
Sesuai rencana, perahu Pak Sahar bersandar kembali di salah satu “dermaga rumahan” Pulau Papan jauh sebelum matahari tergelincir di ufuk. Aktivitas warga masih berjalan. Seorang ibu menimbang gurita segar hasil tangkapan nelayan di pasar dadakan dekat rumah warga.
Itulah momen terakhir saya di Pulau Papan. Kami harus bertolak ke Ampana karena kapal tidak datang setiap hari. Kapal besar datang hanya pada hari Minggu, Selasa, dan Jumat.
Soal jadwal kapal sebenarnya bisa jadi berkah sekaligus ujian. Berkah sebab saya bisa berlama-lama di “negeri kepulauan” ini. Namun, bisa pula dianggap kendala transportasi karena saya tidak bisa bebas bepergian atau “pulang” sewaktu-waktu.
Kendala lain, telepon seluler sama sekali tidak menangkap jaringan sinyal di Pulau Papan. Alhasil, drone yang saya bawa—sekaligus saya impikan bisa merekam kehidupan masyarakat lokal—tidak dapat terbang. Meski sedikit kecewa, rasa itu terobati oleh kesan mendalam setiap perjalanan di pulau ini yang sampai kapan pun tak akan terlupakan.