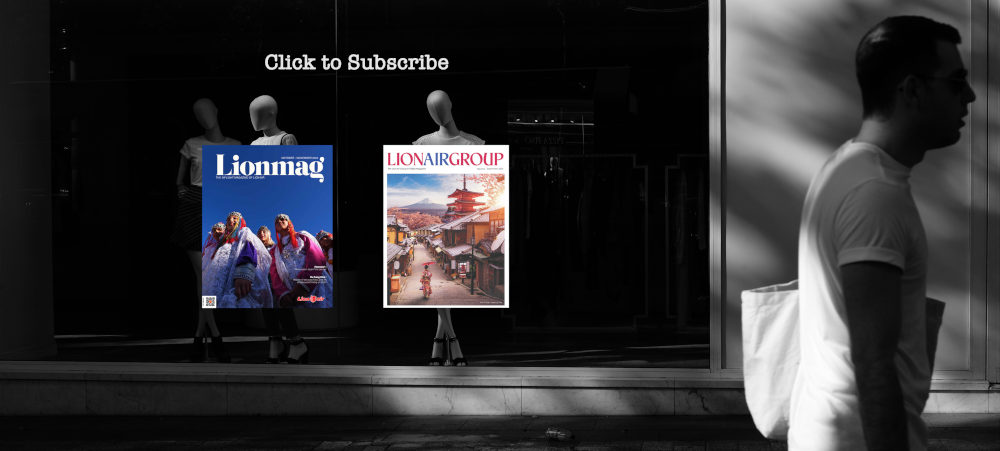PERTAMA kali kita bertemu, saya masih ingat, di kamar kerja Pak Muhammad Nur, yang waktu itu masih menjabat Dubes RI di Perancis. Kalau tidak salah ingat, pertemuan itu berlangsung dalam bulan Agustus 1978, empat tahun yang lalu. Waktu itu udara kota metropolitan Paris hangat, cerah dan terang dalam pelukan musim panas.
Masih segar dalam ingatan saya, beberapa keping dialog kita, di antaranya:
"Anda betah tinggal di Eropa?" tanya Anda, yang saya jawab tanpa ragu-ragu:
"Tidak, cuma karena terpaksa. Seandainya nafkah yang saya peroleh di sini sebagai pegawai lokal kedubes kita di Perancis dapat saya peroleh separuhnya saja di Indonesia, maka saya putuskan pulang!"
"Apa yang membuat Anda tidak betah?", tanya Anda selanjutnya. Kemudian saya jawab:
"Kehidupan di sini sudah sangat merutin. Membosankan. Di sini kita dijajah waktu teramat ketat. Di sini hubungan antarmanusia terlalu teratur, formal, individualistik dan serba afspraak. Saya sebagai orang Indonesia merasakan semua ini tidak manusiawi lagi. Mungkin karena terbiasa hidup di tengah-tengah keluarga yang begitu akrab satu sama lain, yang memang merupakan gaya dan watak khas bangsa Indonesia."
BACA JUGA : Dokter Jenius
Ketika kita berada di sebuah restoran Vietnam yang terkenal di Paris setelah berdialog panjang lebar, kita kemudian menyimpulkan: "Keramah-tamahan masyarakat Indonesia dan kecantikan alam Indonesia akan kita rasakan sebagai nomor satu di dunia kalau kita sempat bermukim beberapa waktu di luar negeri. Artinya, hal itu tidak akan terasa, kalau kita hanya terpendam terus-menerus di bumi sendiri. Karena kita tidak punya bahan banding.
Anda tentu saja juga masih ingat, ketika kita jalan-jalan dan kemudian singgah di sebuah kantor pos. Di kantor pos ini, seperti juga halnya di kantor-kantor lain, tidak ditemukan pegawai yang duduk malas-malasan sambil ngobrol dan mengepulkan asap rokok. Di sini, kalau orang sedang bekerja, dilarang merokok, dan larangan ini telah terhayati sebagai nilai sehingga tidak membutuhkan lagi peringatan tertulis atau verbal dari atasan atau dari mana pun. Kalau kita bicara soal disiplin kerja ini, memang kita menjadi sedih sebab di Indonesia masih banyak terdapat "kesibukan" main domino pada jam-jam kerja justru di kantor-kantor pemerintah.
*****
SEJAK Pak Nur meninggalkan posnya sebagai dubes RI di Perancis, saya ikut meninggalkan Paris. Kalau Pak Nur pulang ke tanah air, saya sekarang bertempat tinggal di salah satu kota terpenting di negeri Belanda, Amsterdam. Saya tahu Anda pernah juga berkunjung di kota ini. Di kota "kanal" ini, saya hidup sebagai orang swasta berkat bantuan seorang Belanda yang pernah tinggal di Bogor.
Seperti Anda ketahui, di sini cukup banyak orang Indonesia. Mau makan soto Madura, ada; mau makan gado-gado atau masakan Padang, juga ada. Tetapi maaf, jangan dulu cari coto Makassar sebab jenis masakan kesayangan Anda ini belum ada di kota yang cukup ramah ini.
Penduduk kota tua, yang dulu bernama Amstelledamme, tampak bebas, terbuka dan toleran. Saban kita berjumpa, terutama gadis-gadisnya, pertanyaan yang pertama-tama dilontarkannya: "Anda berbahasa apa?" Maksudnya, mereka akan melayani Anda dengan intim lewat bahasa yang rata-rata mereka kuasai, yaitu: Inggris, Jerman, Perancis, dan tentu saja, bahasa Belanda. Apalagi gadis-gadis yang mencari nafkah hidupnya di sailors quarter’s atau di red light district.
Sebagai kota maksiat (kalau Anda tega menggunakan istilah ini) satu-satunya saingan Amsterdam di dunia adalah Hamburg. Di Amsterdam ini bertebaran sex-shops, night clubs, porno theatres, private houses dan segala macam tempat yang menyuguhkan aktraksi seks yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya.
Pada sisi lain, di sebelah kehidupan seks yang mahadahsyat itu, pada hari-hari tertentu, kota Amsterdam tenggelam dalam alunan dan gema lonceng gereja. Dua alur kehidupan ini berjalan sendiri-sendiri dan sama-sama kuat mengimbau umatnya. Yang satu menawarkan sorga sekarang, sedangkan yang lainnya menjanjikan sorga di hari kemudian. Sorga yang satu dibeli dengan uang, sedangkan sorga yang lain bakal diperoleh dengan iman. Amsterdam menyerahkan kepada kita untuk memilih salah satunya, atau barangkali ada jalan memilih kedua-duanya?
*****
DI KOTA Amsterdam ini Anda jumpai banyak kanal dan jembatan tua yang antik. Kota ini juga dijuluki orang 'kota museum' karena di dalamnya terpelihara dengan baik lebih enam ribu bangunan bersejarah, di antaranya masih banyak peninggalan abad XVII. Pemerintah dan masyarakat di sini bersama-sama memelihara barang yang sangat berharga sebagai kebanggaan sejarah yang tak ternilai harganya.
Berbicara soal kebanggaan sejarah ini, saya teringat keluhan Anda waktu kita bertemu di Paris empat tahun yang lalu. Anda bercerita tentang nasib sebuah benteng yang nyaris dihancurkan sama sekali pada tahun lima puluhan oleh orang-orang yang tidak berkesadaran sejarah. Nama benteng itu Fort Rotterdam atau lebih dikenal dengan nama Benteng Ujung Pandang. Untunglah waktu itu bangkit sejumlah budayawan, sejarawan, seniman dan wartawan yang gigih menentang keinginan itu. Perjuangan mereka, kata Anda, boleh dikatakan berhasil, tetapi tidak penuh. Sebabnya, kanal di sekitar benteng itu terlanjur ditimbuni dan di atasnya dibangun sejumlah gedung yang secara sempurna menutupi benteng dari segala sisi, kecuali dari depan yang menghadap laut.
Kalau ada bangunan atau gedung bersejarah di Kota Makassar, bagaimana nasibnya sekarang? Saya yakin pemerintah dan masyarakat kota Anda ini sudah jauh lebih maju dan sadar untuk tidak main bongkar atau main pugar seenaknya. Semoga. Kapan Anda ke Eropa lagi? Wassalam.*****
* Tulisan ini bagian dari buku kumpulan tulisan Arsal Alhabsi "WARTAWAN KOBOI', dimuat di Harian Fajar tahun 1994-1996 dalam Kolom : Bacaan Sekolom Sambil Minum Kopi.