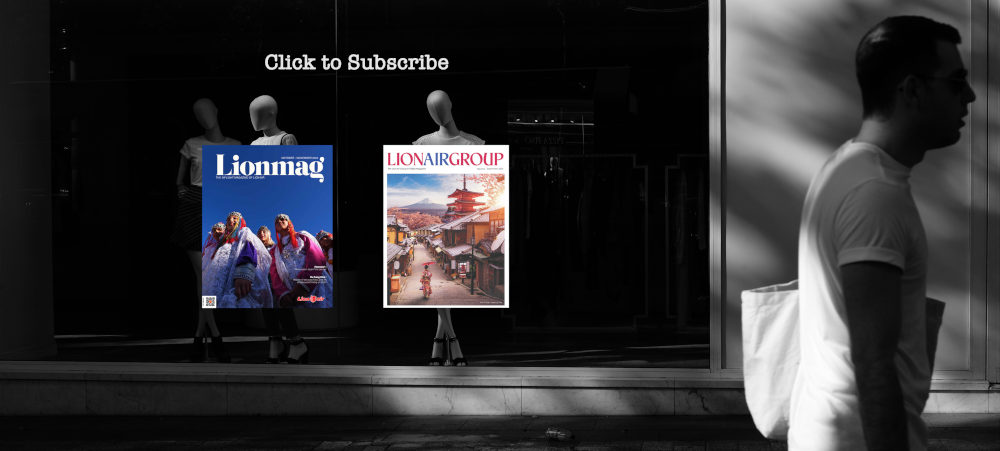Di sebuah ruang pamer tenang di Museum Batik Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, lembar-lembar kain terbentang. Seolah membuka halaman hidup dari sejarah panjang batik Nusantara. Motifnya beragam; dengan angka tahun pembuatan yang berbeda-beda.
Berjalan menuju ruangan paling ujung, di segmen terakhir area pamer museum, pengunjung dapat menikmati ekshibisi khusus yang mengangkat tema ‘motif ayam’. Dari babon angrem hingga sawunggaling, dari keraton Solo hingga pesisir Cirebon, batik motif ayam kini menjadi tema pameran temporer ‘KukuruYUK!: Ragam Motif Ayam dalam Batik Indonesia’. Pameran berlangsung hingga akhir Desember 2025 mendatang.
Bagi kurator pameran, Swa Setyawan Adinegoro, ayam lebih dari sekadar hiasan. “Awalnya kami ingin menelusuri motif hewan secara umum, tapi ternyata hanya dari ayam saja sudah sangat kaya,” ujarnya. Dari simbol ritual hingga ornamen dekoratif, dari klasik hingga kontemporer, kata Swa, motif ayam menghadirkan narasi yang hidup dan berlapis.
Lebih dari sekadar Ritual, Lebih Filosofis dibanding Ornamen Kontemporer
Ayam sudah lama hadir dalam batik — sebagai simbol, pengingat, dan penghias. Dalam tradisi Jawa, ayam bukan sekadar hewan piaraan. Ia adalah lambang kehidupan dan perlindungan.
“Motif babon angrem, misalnya,” jelas Swa, “menunjukkan kasih sayang dan sisi feminitas seorang ibu. Ia biasanya digunakan pada upacara mitoni atau tujuh bulanan — sebuah simbol harapan agar bayi lahir selamat.”
Sebaliknya, motif sawunggaling menampilkan ayam jantan yang gagah, simbol maskulinitas dan ketangkasan, bahkan memiliki dimensi sejarah. “Motif ini muncul atas gagasan Presiden Sukarno yang ingin ada batik bersifat nasional; bukan hanya batik dengan kekhasan seperti Yogyakarta, Solo, atau Pekalongan.”
Dari pameran temporer ini pula, pengunjung bisa mempelajari kekhasan sekaligus kekayaan batik dari tiap-tiap daerah di Indonesia. Batik keraton dan batik pesisir, contohnya, hidup dari dua dunia yang berbeda. Batik keraton taat pada pakem dan filosofi yang ketat, pewarnaannya cenderung sogan kecokelatan, simboliknya dalam. Sementara batik pesisir lebih ekspresif, penuh warna, dan berkembang untuk perdagangan.
“Itu memberi kebebasan bagi pembatik untuk bermain warna dan bentuk. Makanya, warna-warnanya jauh lebih berani,” kata Swa. Cirebon menjadi contoh unik, menggabungkan tradisi keraton dan pesisir — termasuk babon angrem dengan latar biru, memberikan nuansa berbeda dari yang umum ditemui di Solo atau Yogyakarta.
Persilangan Budaya: Dari Lasem ke Eropa
Seiring berkembangnya industri batik pertengahan abad ke-19, pengaruh lintas budaya mengalir deras. Swa menjelaskan, industri batik mulai booming sejak 1840-an. Bukan hanya orang Jawa yang membatik, tapi juga keturunan Tionghoa dan Eropa.
“Dari situlah muncul batik-batik Lasem bercorak Tionghoa, atau batik dengan pengaruh Eropa yang kemudian lebih populer disebut ‘batik Belanda’,” jelasnya, merujuk inisiatif perempuan Indo-Eropa yang meminta para pembatik meniru ilustrasi dari benua lain seperti buket bunga, bahkan putri salju.
Selain itu, motif-motif seperti banji — menyerupai pola swastika yang melambangkan keseimbangan — kadang memuat figur ayam di dalamnya. “Dalam budaya Tionghoa, ayam adalah salah satu shio. Jadi, makanya pun berbeda.”
Contoh lainnya adalah karya KRT Hardjonagoro atau Go Tik Swan, keturunan Tionghoa yang diapresiasi Swa sebagai sosok yang ‘sangat njawani (memiliki kesantunan dalam bersikap laiknya orang Jawa yang mengadopsi serangkaian tata krama dalam kehidupan). Dari tangannya lahir sawunggaling dengan ekor menyerupai phoenix.
Seiring waktu, fungsi batik juga bergeser. Dari ritual dan simbol status sosial, kini batik menjadi elemen dekoratif dan ekspresi artistik kontemporer. “Tapi itu tidak salah — karena dengan membatik sama artinya kita sudah berupaya melestarikan batik.”
Dalam pameran, pengunjung dapat melihat evolusi itu secara nyata. Dari kain lawas berangka tahun 1940-an hingga produksi terbaru tahun 2000-an. Salah satunya, motif “Ayam Asuh” dari Sidoarjo, tahun 2000-an, yang menampilkan keluarga ayam dalam gaya ceria dan kontemporer. “Lucu, tapi bermakna. Bukti bahwa ayam tetap hidup dalam batik, bahkan setelah berabad-abad.”
Warisan yang Terus Hidup
Museum Batik Indonesia memiliki lebih dari 900 kain, dari tahun 1900-an hingga 2025. “Banyak koleksi hibah dari Yayasan Batik Indonesia, tapi ada juga pinjaman pribadi, seperti kain pelo ati dan nitik cakar yang kami tampilkan di pameran ini,” jelas Swa.
Karena itu pula, proses kurasi sangat penting. Dari puluhan kain bercorak gambar ayam, hanya yang paling representatif dan sesuai ruang yang dipilih. “Tujuannya agar pengunjung tidak overwhelmed, tapi tetap dapat merasakan kekayaan motif dan cerita di baliknya,” kata Swa.
Pameran ini juga mengajak pengunjung menafsirkan sendiri makna motif. “Kenapa ayam begitu dekat dengan manusia? Mungkin karena kita melihatnya setiap hari, dari perilakunya lahirlah simbol dan makna.”
Menurut Swa, batik bukan sekadar kain. Ia adalah arsip hidup, menyimpan cerita zaman, filosofi, dan budaya. Dari ayam yang sederhana hingga pengaruh Eropa dan Tionghoa, batik Indonesia adalah cermin kreativitas dan identitas bangsa.
Tentang Kurator
Swa Setyawan Adinegoro tumbuh di Yogyakarta, dengan latar belakang arkeologi Universitas Gadjah Mada. Sebelum bergabung di Museum Batik Indonesia, ia sempat bertugas di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta.
“Arkeologi dan batik sama-sama berbicara tentang kebudayaan,” katanya. “Semakin kita belajar tentang batik, semakin kita sadar bahwa kita tidak tahu banyak; betapa luas dan dalamnya warisan ini. Nama motif bisa sama tapi bentuknya berbeda di tiap daerah. Itu menarik sekali.”
Bersama tim konservator dan tata pamer, Swa berharap pameran ini tak hanya mengajak orang menikmati keindahan, tapi juga memahami batik sebagai bahasa budaya yang hidup.
“Batik itu seperti arsip yang bisa kita kenakan,” ujarnya pelan. “Ia menyimpan cerita tentang zaman, gender, dan pandangan hidup. Dan ayam — sederhana tapi penuh makna — hanyalah salah satu pintunya.”
Museum Batik Indonesia berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, kecuali Senin dan hari libur nasional(*)