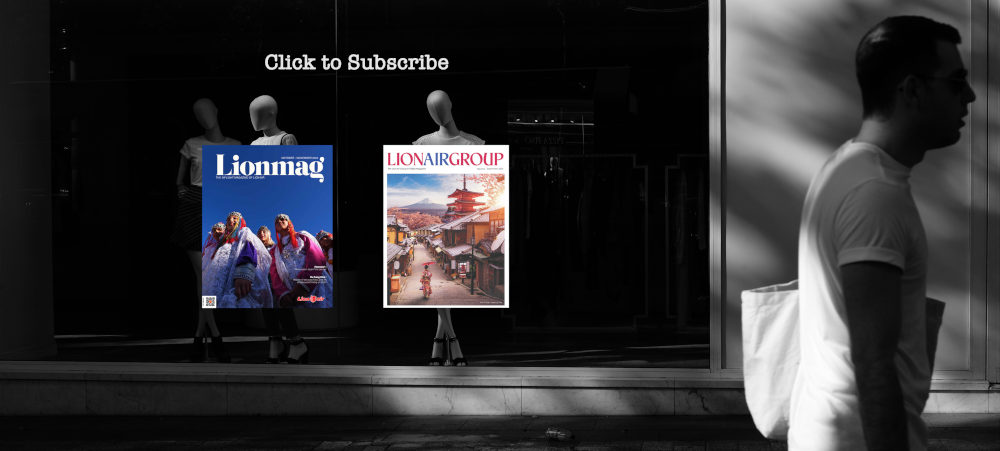Di jantung Timor, pegunungan batu-batu berkabut menyimpan mitologi berhikmah.
Rumput-rumput desa Taiftob di pegunungan Mollo masih kuyup berembun ketika saya mengekori langkah Fun Oematan menuruni lereng bukit di belakang rumahnya. Bocah itu berjalan tanpa banyak bicara, sedangkan ayahnya, Willi Oematan, asyik berkisah tentang mendiang kakek-neneknya yang legendaris. Selain kami bertiga, teman saya, Dicky Senda, penulis yang juga warga desa Taiftob pun turut serta. Kami sedang mencari ‘harta karun.’
“Saya dapat!!,” tiba Fun berteriak sembari menunjuk ke bawah belukar. Mata kami terarah dengan segera. Oh! Harta pertama kami, Favolus tenuiculus, sekumpulan jamur putih dengan topi melebar yang termasuk dalam jenis Polypores tak beracun. Diserahkannya jamur itu ke tangan saya. “Dalam bahasa Dawan jamur disebut Pu’u. Yang ini namanya Pu’u Paku,” urai Willi Oematan. Kami memang sedang berburu jamur, inilah harta karun pegunungan Mollo yang menyembul di musim penghujan.
Perkenalan saya dengan jamur di pegunungan Mollo terjadi sehari sebelumnya, saat Dicky membawa saya ke hutan pinus Fatukoto. Di dekat telaga yang bermandi kabut, kami bersua pria-pria penggembala yang menelusuri hutan itu mencari jamur. “Pu’u Ajaob,” kata mereka menerangkan nama jamur yang muncul di hutan pinus tersebut, satu varian Tricholoma dengan tongkol pendek - mungkin sama jenisnya dengan Jamur Matsutake yang tersohor di Jepang karena sama-sama tumbuh di hutan pinus yang sejuk. Setelah pertemuan itu, saya jadi ingin tahu lebih banyak tentang jamur-jamur di daerah ini. Selain Pu’u Paku dan Pu’u Ajaob, ada pula Pu’u Maon Ana yang tumbuh di sekitar pohon kemiri dan Pu’u Atef yang muncul di padang pohon kayu putih.
Hasil perburuan kami nikmati saat makan siang. “Saya ingin menulis cerita tentang jamur pegunungan Mollo,” Dicky berujar. “Boleh juga. Barangkali ada dongeng lokal terkait Pu’u-Pu’u ini,” balas saya. Dicky adalah penulis yang dalam buku-bukunya gemar mengangkat tema-tema lokal berbalut mitos maupun tambo. Beruntunglah dia tinggal di pegunungan Mollo. Orang-orang disana memandang tiap elemen alam pegunungan mereka secara metafor. Saya yakin, penulis aliran seperti dia tidak akan kehabisan materi cerita.
Fatu Nausus & Misteri Kera Putih
Perjalanan saya ke pegunungan Mollo di Timor Tengah Selatan ini adalah kunjungan ulang selepas beberapa tahun berlalu. Keadaannya tidak jauh berubah. Akses jalan yang masih sederhana dan suasana hening yang menyelimuti hari.
Jika kedatangan sebelumnya saya banyak menghabiskan waktu di Fatumnasi, kali ini saya lebih betah di Taiftob. Dicky mendirikan sebuah komunitas yang menggali ulang cerita-cerita rakyat setempat, dan itu jadi magnet bagi saya. Mollo adalah janabijana yang ideal untuk kisah-kisah mitologi, sebuah negeri di balik kabut yang menyimpan babad-babad keramat.
Suatu hari yang dibayangi gerimis, saya pergi ke kaki Fatu Nausus, gunung marmer yang kelihatan jelas dari penjuru pegunungan Mollo. Hutan pohon Ampupu dan pinus saling bersisian di sela-selanya memberi panorama segar yang tidak butuh didandani monumen apa-apa. Di musim penghujan seperti sekarang ini, tiap jengkal alamnya tampak sentimentil.
Sebuah komplek penginapan etnik membuka gerbangnya untuk saya masuki. Rumah-rumah bundar beratap alang-alang berjejer dengan kebun sayuran dan murbei liar di buritan. Tidak ada suara ingar-bingar, hanya anjing penjaga yang menyalaki burung-burung Ara Timor (Timor Figbird) yang nakal. Entah kenapa saya menyukai kesan ugahari dan agak telantar dari tempat ini.
Di depan mata saya gunung marmer Fatu Nausus terpapar nyata. Tampuknya lancip cadas. Badannya putih pucat dan sebagian dikerubuni tumbuhan hijau bak gundukan sarang raksasa tawon hijau Agapostemon.
Fatu Nausus melambangkan payudara, pemberi kehidupan. Itulah sebabnya batu ini dipandang keramat, tempat dilaksanakan ritual-ritual adat. Saya pernah membaca bahwa bagi orang-orang Dawan di Mollo, setiap unsur-unsur alam menggambarkan anggota tubuh manusia; hutan serta pepohonan adalah rambut, sungai dan air adalah darah, tanah adalah daging, bebatuan adalah tulang. Oleh karenanya pemanfataan sumber daya alam musti dibarengi dengan kesadaran kosmologis.
“Perhatikan Bukit Anjaf yang berada di tengah-tengah ini. Jika mujur, matamu bisa menangkap kelebat sosok kera putih, hewan sakral Fatu Nausus,” bisik pelan Nando, lelaki paru baya yang menemani saya hari itu. Gerimis membuat saya tertegun di bawah atap pondok, tapi mata saya terus menatap ke arah yang ditunjuk Nando. Setahu saya pulau Timor identik dengan buaya sebagai totem etnik, kita bisa menemukan gambar buaya dimana saja dengan beragam kisahnya. Baru di Fatu Nausus ini saya dikenalkan kera putih sebagai makluk sakral lainnya.
“Kera putih itu jelmaan leluhur, penjaga pegunungan Mollo. Bila alam tempat tinggalnya diusik, kemelaratan akan muncul,” ujar Nando lagi. Dia menunjuk sisi bukit yang terpotong, bekas penambangan marmer bertahun-tahun lampau. “Itu contohnya. Bukit-bukit di Mollo adalah bukit marmer, katanya marmer terbaik di dunia. Investor asing datang, lalu bukit-bukit dibela, marmer diangkut. Bencana kekeringan melanda pegunungan Mollo, karena mata air mengering. Beruntunglah kemudian warga sadar dan melakukan aksi penolakan tambang tanpa mempedulikan intimidasi,” lanjutnya. Saya melihat potongan-potongan batu marmer tersisa di kaki Fatu Nausus, jadi saksi tentang eksploitasi alam.
Hingga gerimis usai berganti pelangi, sosok kera putih itu tidak jua nampak. Namun mitologinya yang berkesinambungan dengan peristiwa nyata di pegunungan ini merupakan narasi pembelajaran berhikmah.
Batu-Batu Identitas
Keterikatan orang Mollo dengan batu-batu sangat kuat. Tiap klan-klan keluarga memiliki batu sakral. Dalam memulai hal-hal penting dalam hidup keluarga, batu-batu tersebut dikunjungi dan diupacarai. Relasi ini mengingatkan saya pada orang Toraja di Sulawesi, yang menjadikan batu sebagai tempat peristirahatan terakhir mereka. Adakah pertalian kultur antara Mollo dengan Toraja? Kedua etnis ini sama-sama tinggal di pegunungan.
Batu-batu juga menjadi penjuru sebuah kampung, tengara persekutuan. Di Taiftob sendiri ada Fatu Napi, batu yang tebingnya berwarna merah, dijadikan sebagai penanda desa. Dicky dan Willi Oematan membagikan kisah yang sama tentang Fatu Napi, bahwa dulu banyak kijang yang muncul secara ajaib di kaki bukit itu.
Seminggu setelah saya pulang, Dicky mengirimkan satu puisi yang ditulis seorang anak, judulnya “Tubuhku Batu”. Saya merinding membacanya, lantas mengenang kalimat Andy Goldsworthy, environmentalis asal Inggris, katanya, “Sebongkah batu mendarah daging dengan kenangan-kenangan geologis dan historis.” Di pegunungan Mollo ungkapan itu sangat kentara dihidupi oleh penduduknya. Saya juga ingat, ketika di Fatumnasi dulu, Mateos Anin, juru kunci Gunung Mutis yang lihai memanggil binatang lewat melodi sulingnya pernah berucap, “Batu adalah identitas kami. Jika batu-batu lenyap, kami tak tahu menyebut diri kami siapa.”
Tanpa batu-batu, tambo janabijana Mollo tak akan ada. Tak ada burung-burung Ara, tak ada pinus, tak ada kayu putih, tak ada jamur. ***