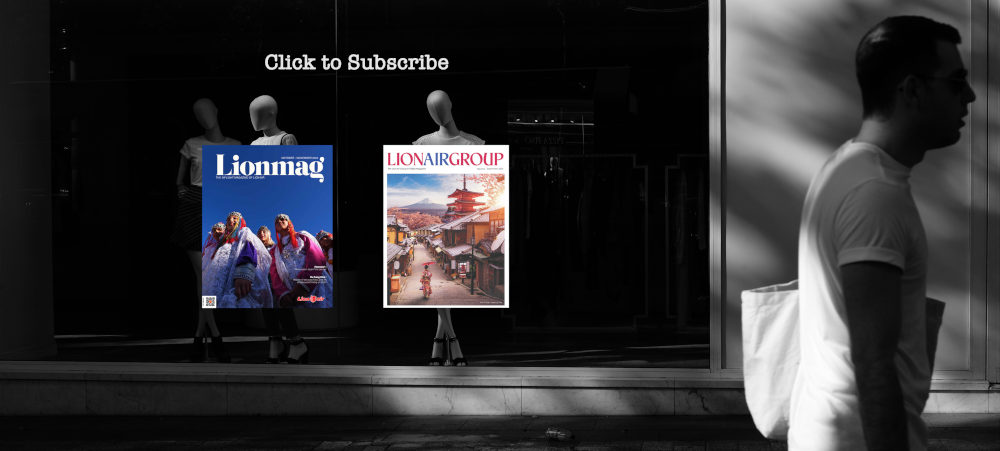SEORANG sastrawan wanita terkemuka Indonesia pernah saya tanya begini: "Andai kata Anda diberi kesempatan memilih atau menetapkan tambahan umur, Anda inginkan berapa tahun lagi?" Pertanyaan yang barangkali agak kedengaran janggal ini dijawabnya datar dan dingin: "Yang saya inginkan cuma sepuluh tahun saja." Saya tidak duga jawabannya berbunyi demikian karena umurnya sekarang baru empat puluhan. Jika ditambah sepuluh tahun, berarti usia yang diinginkannya cuma lima puluhan tahun. Usia di bawah enam puluh tahun rasanya masih cukup muda.
Tentu saja jawaban sastrawan wanita itu memancing pertanyaan saya selanjutnya: "Kenapa Anda hanya mendambakan usia yang sependek itu?" Ia tidak langsung menjawab matanya menembus mata saya. Saya tidak mau kalah, mata saya pun menembus matanya. Ia lalu tersenyum. Matanya berkedip beberapa kali, saya kira tanda menerima kekalahan kemudian mulutnya mengeluarkan kata-kata dengan suara berbisik: "Mas Arsal, untuk apa umur panjang kalau hanya untuk menambah beban keluarga, beban masyarakat. Umur panjang memang berguna asal tetap sehat dan kreatif. Saya kuatir, saya bakal lebih sakit-sakitan kalau usia saya mendekati enam puluh tahun."
Bisikannya itu membuat saya terkesima. Usianya sekarang baru empat puluh lima tahun, tetapi secara teratur harus memeriksakan keadaan kesehatannya kepada seorang dokter spesialis kandungan. Di dalam rahimnya tumbuh sejenis tumor yang sudah sekian kali diangkat tetapi selalu tumbuh kembali. Ia telah melakukan apa saja yang mungkin untuk menjinakkan tumor itu, tetapi gagal semua. Namun ia tetap bersemangat, tetap kreatif. Artinya, secara kejiwaan ia masih sanggup menaklukkan gangguan kesehatan fisiknya itu. Ia sanggup melewatkan hari- harinya dengan perasaan aman dari gangguan tumor yang tak mau copot akarnya itu. Tetapi kekuatan jiwanya itu sampai kapan bertahan? Ia menetapkan limit: sepuluh tahun, tidak lebih. Waktu yang telah diberi bingkai, batas, harus diisi padat. Program disusun rapi. Tak boleh timbul celah yang sia-sia. Dalam sepuluh tahun mendatang ini, sekian novel, sekian kumpulan cerpen harus lahir. Semua ini demi lebih memperkokoh kehadirannya sebagai sastrawan. Juga sebagai tanda terima kasihnya kepada kehidupan, kaumnya dan kemanusiaan
*****
BELAKANGAN ini saban saya ke Jakarta tidak perlu lagi menginap di hotel. Dua tahun yang lalu orang tua saya pindah ke ibukota dan membeli rumah di sana. Di rumah yang cukup luas itu tersedia kamar khusus untuk saya. Ini sangat menghemat. Juga keakraban dengan kakak dan adik-adik saya terpelihara.
Tetapi suasana yang selalu saya dambakan itu, mengalami gangguan. Setiap saya duduk santai di teras, depan rumah, selalu kedatangan tamu, seorang tua, yang tidak pernah bercerita lain kecuali tentang mimpinya semalam.
Pada mulanya kehadiran tamu ini terasa tidak mengganggu. Tetapi dari hari ke hari, ceritanya tidak pernah bergeser dari mimpi ke mimpi yang sama. Ketemu pagi atau ketemu sore, tetap cerita tentang mimpi. Wah, bosan. Bosan sekali. Bahkan berkembang menjadi semacam teror. Teror mental. Akhirnya, saya merasakan sesuatu yang aneh, katakanlah itu sejenis ketakutan untuk duduk di depan rumah. Takut kedatangan tamu yang "setia" itu. Takut mendengar ceritanya. Takut mendengar mimpinya.
*****
PENGALAMAN saya dengan tamu yang selalu menjajakan mimpinya itu, mengingatkan saya kembali pada ucapan sastrawan wanita, sahabat saya yang satu-satunya memanggil dengan sebutan "Mas Arsal" bahwa umur panjang memang berguna asal tetap sehat dan kreatif. Sebaliknya, ketuaan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan jika diwarnai hanya dengan kepikunan. Kepikunan meniadakan keberadaan manusia. Manusia yang tak mampu lagi eksis juga berarti tak mampu berekspresi secara kreatif. Dalam keadaan seperti ini, seorang manusia sudah mati secara mental spritual walaupun secara fisik masih hidup karena jantungnya masih berdetak. Saya kira saat meninggal yang paling ideal ialah saat sebelum kita menjadi "sampah".*****
* Tulisan ini bagian dari buku kumpulan tulisan Arsal Alhabsi :"WARTAWAN KOBOI'.