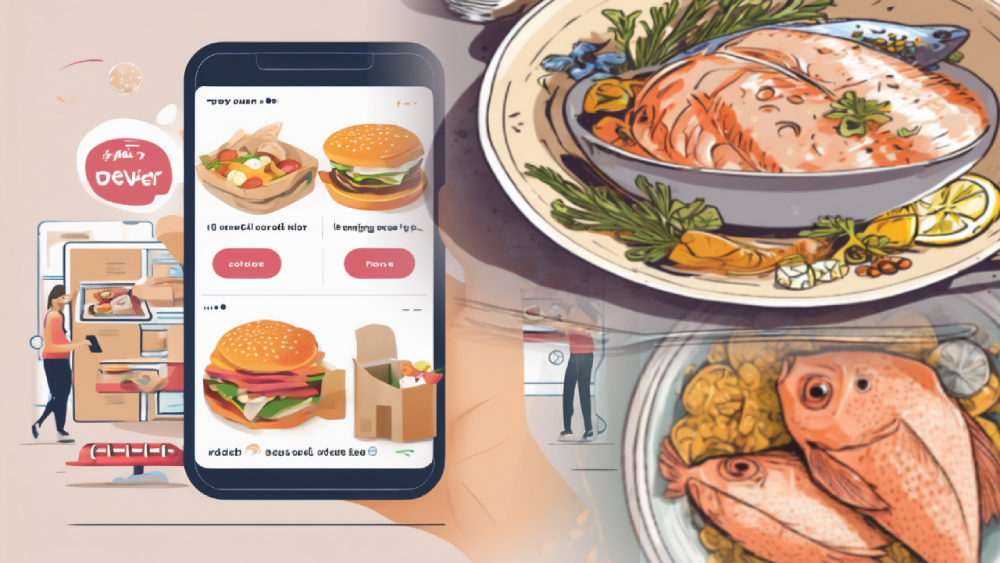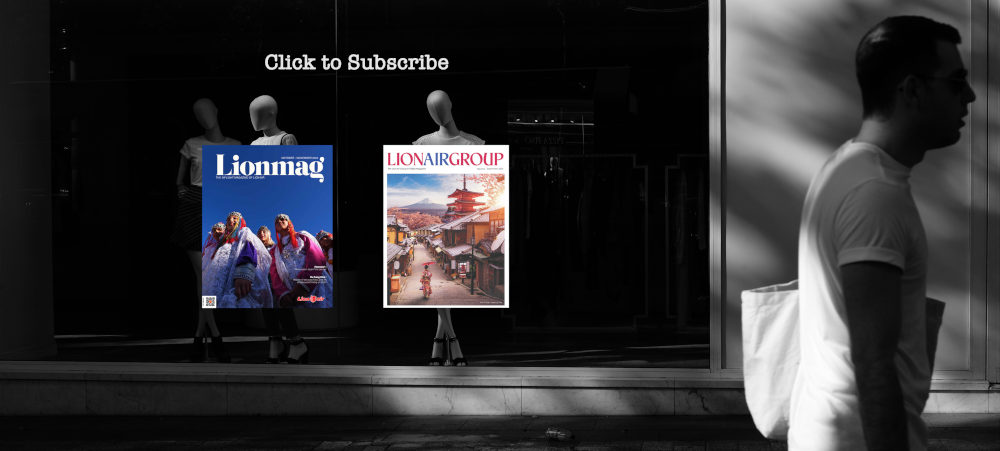Dapur rumah kini berada di ambang senyap. Ia tidak roboh, tidak pula benar-benar ditinggalkan, tetapi perlahan ditarik menjauh dari pusat kehidupan. Nyala kompor semakin jarang terlihat. Bunyi wajan kian asing. Dapur seperti ruang yang kehilangan gravitasi—mengambang di rumahnya sendiri, nyaris tanpa peran.
Di era smartphone, masakan tidak lagi ditentukan oleh kecekatan tangan ibu atau resep rahasia nenek yang diwariskan dari ingatan ke ingatan. Ia ditentukan oleh jari-jari yang menari di layar. Satu sentuhan cukup untuk memanggil makanan dari luar. Satu gesekan cukup untuk memilih rasa. Resep berpindah dari ingatan kolektif ke algoritma. Api digantikan oleh notifikasi. Aroma digantikan oleh estimasi waktu tiba.
Perubahan ini tampak sepele, tetapi sesungguhnya ia menandai pergeseran kebudayaan yang dalam. Dapur, yang selama berabad-abad menjadi pusat rumah, kini terdorong ke pinggir. Dalam banyak hunian modern, dapur diperkecil, disederhanakan, dan bahkan disamarkan. Seolah memasak adalah aktivitas sampingan, bukan aktivitas utama. Rumah pun berubah fungsi. Ia bukan lagi ruang mengolah hidup, melainkan tempat singgah antara pesanan satu dan pesanan berikutnya.
Padahal, dapur bukan sekadar tempat memasak. Ia adalah ruang pendidikan pertama. Di sanalah anak belajar menunggu, belajar berbagi, belajar bahwa makanan tidak lahir dari layar, melainkan dari proses. Di dapur kita mengenal asal-usul pangan—beras dari sawah, garam dari laut, api dari energi yang harus dijaga. Dapur mengajarkan etika relasi antara manusia, alam, dan kerja.

Ketika dapur sunyi, yang hilang bukan hanya aktivitas domestik, tetapi juga percakapan. Hilang obrolan kecil sambil mengiris bawang. Hilang tanya sederhana yang penuh perhatian, “Sudah makan?” Smartphone memang mempercepat segalanya, tetapi tidak menggantikan kehangatan yang tumbuh perlahan di antara panci dan tungku.
Secara sosiologis, dapur adalah ruang kohesi. Ia menyatukan ritme keluarga. Banyak kajian menunjukkan bahwa keluarga yang masih meluangkan waktu memasak dan makan bersama memiliki ikatan emosional yang lebih kuat. Dapur memaksa jeda di tengah arus notifikasi. Ia mengajarkan kehadiran, bukan sekadar terkoneksi.
Namun, zaman ini memuja kecepatan. Waktu dianggap terlalu mahal untuk dihabiskan di dapur. Memasak dinilai tidak efisien. Di sinilah paradoks itu bekerja. Kita menghemat waktu, tetapi kehilangan makna. Kita kenyang, tetapi sering kali tidak hangat. Kita bersama secara fisik, tetapi masing-masing sibuk dengan layar.
Quo vadis, dapur rumah? Ke mana hendak kita arahkan? Apakah ia akan menjadi sekadar ornamen interior, atau kita kembalikan sebagai jantung kehidupan? Menghidupkan kembali dapur bukan berarti menolak teknologi, melainkan menempatkannya secara proporsional. Smartphone dapat membantu, tetapi tidak boleh menggantikan perjumpaan.
Saatnya dapur benar-benar beristirahat. Sepi dari beban yang timpang, dari anggapan bahwa itu urusan satu orang. Lalu, bangkit kembali sebagai ruang bersama. Tempat ayah belajar menumis, anak belajar mencuci beras, dan keluarga belajar bekerja sama. Dapur tidak harus mewah. Ia hanya perlu revitalisasi dan kembali menyala.
Di tengah dunia yang serba instan, dapur rumah adalah ruang perlawanan esensial. Di sanalah rumah menemukan denyutnya kembali—pelan, hangat, dan manusiawi.(***)